Oleh: Bangkit Rahmat Tri Widodo
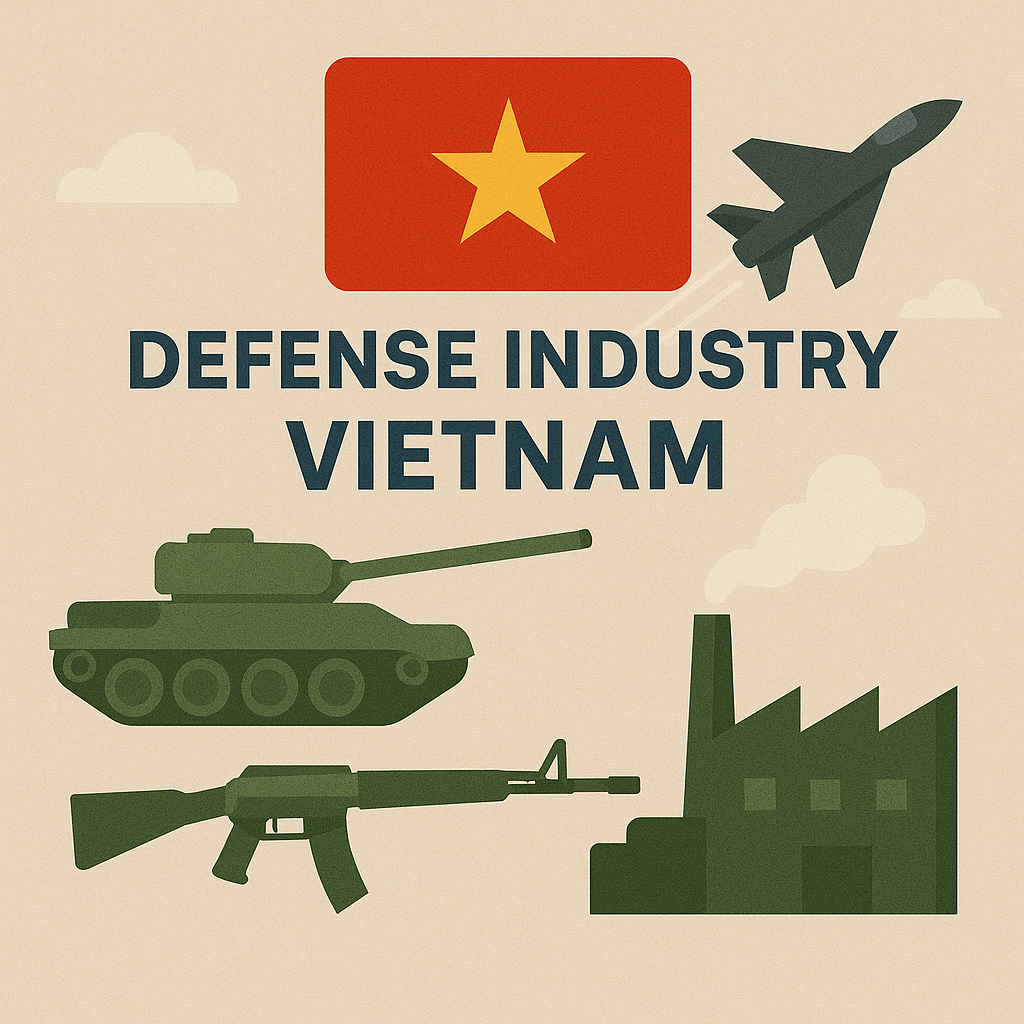
Industri pertahanan merupakan salah satu pilar strategis dalam pembangunan kekuatan negara modern. Ia tidak hanya berfungsi sebagai penopang kebutuhan militer, melainkan juga sebagai motor penggerak industrialisasi, inovasi teknologi, dan penguatan daya saing ekonomi nasional. Bagi negara-negara berkembang, industri pertahanan memiliki dimensi ganda: di satu sisi menjadi sarana untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemasok asing, di sisi lain berfungsi sebagai katalisator pembangunan ekonomi yang lebih luas melalui penciptaan lapangan kerja, alih teknologi, serta penguatan basis penelitian dan pengembangan (Bitzinger, 2003; Hartley, 2007).
Bagi Vietnam dan Indonesia, penguatan industri pertahanan menjadi isu strategis yang semakin mendesak seiring dengan dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Lingkungan keamanan regional ditandai oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan, rivalitas kekuatan besar, serta percepatan modernisasi militer di negara-negara tetangga (Kaplan, 2014). Dalam kondisi demikian, ketergantungan berlebihan terhadap impor alutsista menimbulkan risiko strategis, baik berupa kerentanan terhadap embargo maupun keterbatasan dalam menjamin kesiapan tempur. Oleh karena itu, pembangunan basis industri pertahanan yang mandiri dan berkelanjutan menjadi prasyarat penting bagi kedaulatan pertahanan.
Namun, dilema yang dihadapi negara berkembang cukup kompleks. Kebutuhan modernisasi militer yang cepat kerap berhadapan dengan keterbatasan sumber daya finansial, kapasitas teknologi, dan infrastruktur industri. Di satu sisi, anggaran pertahanan yang terbatas membatasi ruang bagi investasi riset dan produksi domestik. Di sisi lain, ketergantungan terhadap pemasok asing menimbulkan persoalan kemandirian strategis sekaligus melemahkan posisi tawar dalam politik internasional (Matthews & Maharani, 2019). Situasi inilah yang dialami baik oleh Indonesia maupun Vietnam, meski dengan pendekatan kebijakan yang berbeda.
Dalam dua dekade terakhir, Vietnam menampilkan model pengembangan industri pertahanan yang patut dicermati. Sejak tahun 2000-an, negara ini mulai merumuskan strategi pembangunan pertahanan dengan menekankan konsistensi arah politik, penguatan kerangka hukum, serta kebijakan industrialisasi yang bersifat dual-use, yakni memadukan kepentingan militer dan sipil. Vietnam secara cermat memanfaatkan mekanisme lisensi produksi dan kerja sama industri dengan negara-negara besar, khususnya Rusia, namun secara bertahap mengembangkan kapasitas domestik melalui transfer teknologi dan peningkatan kemampuan manufaktur (Thayer, 2017; Nguyen, 2020). Pendekatan ini memungkinkan Vietnam tidak hanya memenuhi kebutuhan militer jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang menuju kemandirian.
Indonesia memiliki relevansi yang kuat untuk mempelajari pengalaman Vietnam. Sebagai negara kepulauan dengan tantangan keamanan maritim yang besar, Indonesia juga menghadapi dilema serupa: modernisasi TNI membutuhkan percepatan, sementara basis industri pertahanan nasional masih menghadapi kendala klasik seperti rendahnya kapasitas riset, keterbatasan pembiayaan, serta lemahnya integrasi antara BUMNIS, swasta, dan lembaga riset (Sukma, 2015; Sebastian & Gindarsah, 2013). Dengan mempelajari strategi Vietnam, Indonesia dapat memperoleh pelajaran penting tentang bagaimana merancang kebijakan yang konsisten, membangun kerangka hukum yang kondusif, serta mendorong model dual-use industry yang berkontribusi bagi pertahanan sekaligus pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, tulisan ini menelusuri bagaimana Vietnam mengembangkan industri pertahanannya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta pelajaran yang dapat dipetik bagi pengembangan industri pertahanan Indonesia di tengah dinamika strategis kawasan Indo-Pasifik.
Tinjauan Literatur
Tinjauan atas literatur industri pertahanan Asia Tenggara menunjukkan bahwa kajian kawasan ini masih lebih jarang dibanding Eropa atau Asia Timur Laut, namun dalam satu dekade terakhir muncul pola umum berupa dorongan import substitution yang berevolusi menuju selective upgrading pada lini tertentu, terutama platform maritim, senjata ringan, dan elektronika pertahanan, dengan intensitas yang bervariasi antarnegara (SIPRI, 2022). Pola variasi ini berkorelasi dengan ukuran pasar, struktur belanja militer, kapasitas industri dasar, serta kualitas tata kelola pengadaan. Small Arms Survey (2024) menegaskan dua friksi utama yang membatasi scaling up, yaitu: rendahnya transparansi rantai nilai, misalnya keterbukaan data nilai tambah domestik, offset, dan lisensi, serta skala produksi yang belum ekonomis, sehingga negara-negara di Indo-Pasifik kerap terperangkap pada low-volume, high-cost equilibrium. Di sisi lain, temuan komparatif menegaskan sentralitas peran negara dalam menopang basis industri pertahanan melalui kebijakan permintaan (pengadaan jangka panjang, standardisasi) dan penawaran (dukungan R&D, insentif fiskal), serta melalui aransemen kooperasi internasional untuk transfer teknologi (ToT) yang terencana (Bitzinger, 2017).
Kerangka ekonomi inovasi memberikan lensa tambahan untuk menjelaskan mengapa beberapa negara di kawasan lebih cepat naik kelas. Literatur latecomer industrialization menyoroti pentingnya kapasitas serap (absorptive capacity), yakni kemampuan aktor domestik memahami, menyerap, dan menyempurnakan teknologi yang diperoleh melalui lisensi, offset, maupun co-development (Cohen & Levinthal, 1990). Kapasitas ini dibentuk oleh investasi jangka panjang pada pendidikan teknik, laboratorium uji, dan organisasi pembelajaran dalam perusahaan milik negara maupun swasta (Lall, 1992). Mekanisme learning by doing dan learning by interacting mempercepat pembentukan kapabilitas desain, dengan syarat terdapat kejelasan jalur produk, dari perakitan, lokalisasi komponen kunci, hingga design authority, serta stickiness kebijakan yang menahan negara untuk tidak terus-menerus melakukan policy resets (Arrow, 1962; Bell & Pavitt, 1995). Di sini, teori path dependence mengingatkan bahwa keputusan awal mengenai mitra, standar, dan arsitektur teknologi dapat menciptakan lock-in yang memudahkan difusi kompetensi atau sebaliknya memperpanjang ketergantungan (Arthur, 1989).
Dalam literatur ekonomi-politik, model “negara pembangunan” (developmental state) dan gagasan embedded autonomy menekankan bahwa kapasitas birokrasi teknis yang otonom namun terbenam dalam jaringan produktif domestik cenderung menghasilkan kebijakan industri yang lebih disiplin, termasuk pada sektor pertahanan yang bernilai strategis dan berisiko tinggi (Evans, 1995; Johnson, 1982). Pada sektor ini, instrumen kebijakan yang banyak dibahas meliputi pengadaan berbasis portofolio multi-tahun, kebijakan offset yang enforceable, konsorsium R&D publik-swasta, serta agenda dual-use yang menjembatani kebutuhan militer dengan pasar sipil untuk mencapai skala ekonomi dan spillover teknologi (Markowski & Hall, 2004). Namun beberapa literatur juga mengingatkan risiko klasik: distorsi alokasi modal, soft budget constraint pada BUMN pertahanan, dan masalah keagenan yang menurunkan insentif efisiensi ketika tata kelola tidak memadai (Megginson & Netter, 2001). Karena itu, penatalaksanaan pengadaan, termasuk transparansi kebutuhan, kompetisi terbatas yang sehat, dan audit kinerja teknologi, menjadi determinan penting kualitas learning domestik (Bitzinger, 2017; SIPRI, 2022).
Khusus Indonesia, studi-studi kebijakan menyoroti kesenjangan antara ambisi kemandirian sebagaimana tertuang dalam UU 16/2012 dan kapasitas implementasi di tingkat program. Hambatan yang paling sering dicatat adalah fragmentasi koordinasi antar-kementerian/lembaga, disinsentif fiskal bagi lokalisasi komponen berteknologi menengah-tinggi, serta volatilitas pembiayaan yang mengganggu kesinambungan learning curve industri (Anwar, 2020; KKIP, 2023). Beberapa literatur juga menggarisbawahi tantangan terbatasnya pasar yaitu: ukuran pesanan domestik yang terfragmentasi lintas variants dan batches membuat pabrikan sulit mencapai skala yang menekan biaya rata-rata jangka panjang, sehingga mendorong ketergantungan pada impor subsistem kritis dan melemahkan bargaining power dalam negosiasi ToT (Anwar, 2020). Agenda dual-use di Indonesia, yang secara teoritis dapat mengentalkan volume permintaan melalui pasar sipil, masih berkembang, dengan beberapa pengecualian di elektronika industri dan telekomunikasi, tetapi belum menjadi poros desain kebijakan industri pertahanan secara menyeluruh (KKIP, 2023).
Sebaliknya, Vietnam dalam literatur kebijakan terbaru kerap diposisikan sebagai case of structured catch-up di Asia Tenggara. Penekanan jatuh pada keterpaduan antara arah politik tingkat tinggi dan kerangka hukum implementatif, misalnya resolusi Politbiro yang kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Industri Pertahanan, Keamanan, dan Mobilisasi Industri No. 38/2024/QH15, lengkap dengan komite pengarah lintas-sektor dan mandat pengembangan basis data mobilisasi industri nasional (Vietnam Law Magazine, 2024). Diskursus kebijakan menempatkan perusahaan dual-use seperti Viettel sebagai jangkar demand–pull dan technology-push sekaligus, yang mempertemukan kebutuhan militer di domain C4ISR dengan pasar sipil 5G, IoT, dan perangkat keras jaringan; konfigurasi ini dipandang menciptakan lintasan pembelajaran yang lebih stabil karena ditopang arus kas non-anggaran pertahanan (Vietnam News, 2025). Walau demikian, beberapa literatur juga mengakui keterbatasan Vietnam pada pembiayaan R&D frontier, ketergantungan pada komponen kunci impor, serta isu transparansi data manufaktur dan ekspor yang membatasi evaluasi independen (SIPRI, 2022; Small Arms Survey, 2024). Dengan kata lain, Vietnam menawarkan template tata kelola yang koheren dan berdisiplin, tetapi belum mengeliminasi seluruh latecomer constraints yang lazim.
Dari sintesis ini dapat dirumuskan tiga threads konseptual yang berguna untuk analisis komparatif Indonesia–Vietnam. Pertama, state capacity and policy coherence muncul sebagai prasyarat agar kebijakan ToT dan offset benar-benar menghasilkan peningkatan kapabilitas, bukan sekadar perakitan. Kedua, absorptive capacity industri dan ekosistem pengetahuan menentukan kedalaman lokalisasi serta kecepatan transisi menuju design authority, khususnya pada elektronika pertahanan, radar, dan sistem kendali misi yang menjadi “otak” platform. Ketiga, dual-use industrialization berperan sebagai pengali skala ekonomi, yang di negara latecomer menjadi pembeda antara siklus proyek yang terputus-putus dan lintasan belajar yang kumulatif. Literatur menunjukkan bahwa ketika tiga elemen ini berjalan serempak dan konsisten antar-rezim kebijakan, path dependence cenderung bergerak ke arah akumulasi kapabilitas jangka panjang; sebaliknya, bila salah satu simpul rapuh, negara kembali pada ketergantungan impor subsistem kritis dan stagnasi nilai tambah domestik (Arthur, 1989; Bell & Pavitt, 1995; Bitzinger, 2017).
Evolusi Historis Industri Pertahanan Vietnam
Sejarah industri pertahanan Vietnam tidak dapat dilepaskan dari pengalaman panjang perang kemerdekaan, konflik ideologis Perang Dingin, serta dinamika regional pasca-1990. Pasca perang Vietnam (1975), negeri ini mewarisi perangkat militer yang sangat heterogen, sebagian besar buatan Uni Soviet, Tiongkok, dan negara-negara Blok Timur. Struktur industri pertahanan domestik kala itu didominasi oleh jaringan pabrik dengan kode “Z” yang tersebar di berbagai wilayah. Pabrik-pabrik tersebut berfungsi lebih sebagai bengkel perawatan (Maintenance, Repair, Overhaul atau MRO) dan fasilitas perakitan senjata standar Soviet, ketimbang sebagai pusat inovasi dan riset. Sejalan dengan pola negara-negara satelit Soviet lainnya, kapasitas inovasi lokal Vietnam sangat terbatas, karena sistem pengadaan dan teknologi didesain untuk tetap bergantung pada pasokan mitra strategis utama, yakni Uni Soviet (SIPRI, 2022).
Keruntuhan Uni Soviet pada 1991 menjadi titik balik penting. Dengan berkurangnya bantuan militer dan akses terhadap pasokan senjata bersubsidi, Vietnam menghadapi dilema strategis. Di satu sisi, kebutuhan modernisasi tetap mendesak mengingat ketegangan regional, terutama di Laut Cina Selatan. Di sisi lain, sumber daya fiskal negara yang terbatas tidak memungkinkan pembelian senjata besar-besaran di pasar internasional. Kondisi ini mendorong lahirnya paradigma baru: membangun basis produksi pertahanan domestik yang lebih mandiri, meskipun dengan kemampuan bertahap.
Memasuki dekade 2000-an, strategi industrialisasi pertahanan Vietnam mulai bertransformasi melalui mekanisme kerja sama berlisensi. Model ini memungkinkan Vietnam memperoleh akses teknologi sekaligus mengakumulasi keterampilan teknis. Salah satu contoh awal yang menonjol adalah produksi senapan serbu Galil ACE buatan Israel di Pabrik Z111, yang menandai masuknya Vietnam ke dalam skema lisensi Barat meski tetap mempertahankan hubungan erat dengan Rusia. Di sektor maritim, kerja sama dengan Rusia menghasilkan kapal cepat rudal Molniya Project 12418, yang diproduksi di galangan domestik seperti Ba Son. Kedua contoh ini memperlihatkan strategi learning by doing: alih teknologi bertahap yang memberi peluang bagi tenaga kerja dan insinyur lokal untuk memahami proses produksi sekaligus meningkatkan kapasitas modifikasi (Army Recognition, 2016; GlobalSecurity.org, n.d.).
Transformasi yang lebih substansial terjadi pada dekade 2010-an, ketika Vietnam mulai melibatkan perusahaan non-tradisional dalam ekosistem pertahanan. Perusahaan telekomunikasi militer Viettel, yang awalnya beroperasi di sektor komunikasi sipil, diberi mandat memperluas riset dan pengembangan di bidang elektronika militer, radar, komunikasi aman, sistem peperangan elektronik, hingga wahana nirawak. Peran Viettel menandai pergeseran paradigma dari industri pertahanan yang berbasis pada pabrik senjata konvensional menuju industri yang mengintegrasikan teknologi tinggi dan inovasi digital. Lebih jauh, keberhasilan Viettel dalam sektor sipil, khususnya pada jaringan 5G dan Internet of Things, mencerminkan pola dual-use innovation, di mana investasi pada riset militer memiliki spillover effect bagi pasar sipil, dan sebaliknya, keuntungan dari pasar sipil memperkuat kapasitas riset militer (Viettel High Tech, 2025a).
Secara analitis, evolusi historis ini menunjukkan tiga fase. Fase pertama (1975–1990) ditandai oleh ketergantungan struktural terhadap Uni Soviet, dengan industri pertahanan berfungsi sebagai perpanjangan tangan logistik. Fase kedua (1990–2010) merupakan fase transisi, di mana Vietnam memanfaatkan skema lisensi untuk mengurangi kesenjangan teknologi sekaligus memelihara kesiapan minimum. Fase ketiga (2010–kini) memperlihatkan konsolidasi strategi menuju kemandirian teknologi dengan fokus pada sektor berteknologi tinggi, terutama melalui integrasi perusahaan dual-use.
Implikasi dari perjalanan historis ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politik-ekonomi. Pertama, keterbatasan pasokan pasca-Soviet memaksa Vietnam membangun mekanisme resilience melalui substitusi impor. Kedua, diversifikasi mitra teknologi (Israel, Rusia, Eropa) memberi Vietnam ruang manuver lebih besar dalam diplomasi pertahanan. Ketiga, pola dual-use yang dikembangkan Viettel memperlihatkan kemampuan Vietnam untuk mengatasi keterbatasan pasar militer domestik dengan memanfaatkan basis sipil, sehingga tercapai skala ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Dengan demikian, evolusi historis industri pertahanan Vietnam menggambarkan lintasan catch-up industrialization yang khas negara berkembang: dimulai dari peran pasif sebagai penerima sistem asing, lalu beralih ke strategi lisensi dan co-production, hingga pada akhirnya mengembangkan kapabilitas mandiri dalam teknologi canggih. Pola ini memperlihatkan bagaimana negara latecomer dapat mengubah keterbatasan menjadi peluang melalui disiplin kebijakan, diversifikasi mitra, dan integrasi antara sektor militer dan sipil.
Kebijakan Strategis dan Kerangka Hukum
Kekuatan fundamental dari industrialisasi pertahanan Vietnam terletak pada konsistensi arah politik yang ditopang oleh perangkat hukum yang operasional. Sejak lama, sistem politik satu partai di Vietnam memungkinkan adanya kesinambungan visi strategis, terutama dalam isu-isu yang dipandang eksistensial seperti kedaulatan dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, Resolusi Politbiro No. 08-NQ/TW tahun 2022 menjadi tonggak penting. Dokumen tersebut menegaskan bahwa pembangunan industri pertahanan dan keamanan nasional harus bergerak menuju kemandirian, modernisasi, serta orientasi ganda (dual-use), yakni integrasi antara kebutuhan militer dan sipil. Resolusi ini bukan hanya deklarasi politik, melainkan instrumen arah strategis yang mengikat lembaga negara, militer, dan industri untuk bergerak dalam kerangka yang sama (The Party’s Journal, 2024).
Implementasi resolusi tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang No. 38/2024/QH15 tentang Industri Pertahanan, Keamanan, dan Mobilisasi Industri, yang disahkan Majelis Nasional pada Juni 2024 dan akan berlaku penuh mulai Juli 2025. Undang-undang ini membawa sejumlah inovasi kelembagaan. Pertama, undang-undang ini mengatur perencanaan industri pertahanan secara jangka panjang dan berbasis prioritas nasional, sehingga meminimalkan fragmentasi serta memastikan keberlanjutan program. Kedua, ia membentuk komite pengarah lintas sektor yang diketuai langsung oleh Perdana Menteri, suatu mekanisme yang memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga. Dengan struktur ini, kebijakan industri pertahanan tidak lagi berada dalam silo institusional militer semata, melainkan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Ketiga, undang-undang ini memperkenalkan mekanisme mobilisasi industri nasional, yaitu pemetaan dan pendayagunaan kapasitas industri sipil untuk kebutuhan pertahanan pada saat krisis atau perang. Hal ini mencerminkan pola total defense economy, di mana batas antara industri sipil dan militer dibuat permeabel demi kepentingan strategis (Vietnam National Assembly, 2024; Vietnam Law Magazine, 2024).
Lebih jauh, UU 38/2024/QH15 membuka ruang bagi partisipasi sektor swasta dan asing dengan tetap menjaga kedaulatan teknologi melalui regulasi ketat mengenai perlindungan rahasia negara dan hak kekayaan intelektual. Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara keterbukaan terhadap investasi asing dan kebutuhan menjaga keamanan nasional. Vietnam belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika ketergantungan pada satu pemasok (Uni Soviet) membuatnya rentan terhadap guncangan eksternal. Dengan regulasi baru, Vietnam dapat mengatur terms of engagement yang lebih menguntungkan dalam kerja sama internasional, memastikan bahwa transfer teknologi menghasilkan absorptive capacity domestik alih-alih sekadar perakitan (Vietnam Law Magazine, 2024).
Dari perspektif teori tata kelola pertahanan, kebijakan Vietnam memperlihatkan praktik yang mendekati model developmental state dalam sektor strategis. Evans (1995) menyebut konsep embedded autonomy sebagai ciri khas negara pembangunan: birokrasi yang relatif otonom dari kepentingan jangka pendek, tetapi cukup terhubung dengan aktor industri untuk memastikan kebijakan implementatif. Dalam kasus Vietnam, birokrasi pertahanan tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga fasilitator integrasi industri sipil-militer, dengan perusahaan jangkar seperti Viettel sebagai ujung tombak. Dengan demikian, UU 38/2024/QH15 dapat dipandang sebagai instrumen formal untuk menciptakan kondisi embedded autonomy dalam industri pertahanan.
Kerangka hukum ini juga menandai pergeseran industri pertahanan dari proyek teknis yang bersifat militeristik menuju bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Dengan menjadikan industri pertahanan sebagai salah satu motor inovasi teknologi, Vietnam menempatkan sektor ini dalam logika security–development nexus, di mana keamanan dan pembangunan tidak lagi dipisahkan secara dikotomis, melainkan saling menopang. Dalam perspektif ekonomi politik internasional, strategi ini memperlihatkan upaya Vietnam untuk keluar dari jebakan negara konsumen (arms importer dependency) menuju status negara produsen berskala menengah (emerging arms producer), sekaligus memperluas daya tawar dalam diplomasi pertahanan regional.
Dengan demikian, kombinasi antara resolusi politik di tingkat partai dan kerangka hukum operasional di tingkat negara menciptakan sinergi yang memperjelas mandat, peran, serta alokasi sumber daya. Sinergi ini menjadikan pembangunan industri pertahanan Vietnam lebih dari sekadar kebijakan teknis militer, melainkan instrumen transformasi ekonomi dan simbol kemandirian nasional dalam menghadapi dinamika Indo-Pasifik yang semakin kompetitif.
Model Pengembangan Kapabilitas
Dinamika pengembangan kapabilitas industri pertahanan Vietnam dapat dipahami dalam kerangka latecomer industrialization dan teori catch-up technological learning, di mana negara-negara berkembang menempuh jalur bertahap dari sekadar perakitan menuju rekayasa balik (reverse engineering) dan akhirnya pencapaian design authority. Vietnam menempuh jalur ini melalui tiga lintasan utama: senjata ringan, platform maritim, dan elektronika/C4ISR.
Pada sektor senjata ringan dan amunisi, Pabrik Z111 menjadi simbol transformasi. Melalui lisensi produksi senapan serbu Galil ACE dari Israel pada 2014, Vietnam tidak berhenti pada fase perakitan, melainkan mengembangkan varian lokal STV-215/380 yang kini menjadi senjata standar Angkatan Darat Vietnam. Kasus ini mencerminkan absorptive capacity yang memadai, yakni kemampuan untuk menyerap teknologi asing dan melakukan modifikasi sesuai kebutuhan nasional (Cohen & Levinthal, 1990). Proses ini menandai peralihan dari sekadar penerima teknologi menuju produsen yang mampu melakukan rekayasa ulang (re-engineering) dan desain adaptif.
Pada sektor maritim, produksi kapal cepat rudal Molniya Project 12418 di galangan domestik menunjukkan peningkatan signifikan dalam kapasitas industri galangan Vietnam. Kerja sama dengan Rusia membuka peluang bagi Vietnam untuk menguasai teknik perakitan kapal perang sekaligus memperdalam kompetensi dalam integrasi sistem senjata, radar, dan kendali tembak. Dari perspektif teori inovasi industri, tahapan ini merepresentasikan bentuk learning by interacting, di mana insinyur lokal memperoleh pengalaman langsung melalui kolaborasi dengan mitra asing, sambil menanamkan keahlian baru yang dapat diaplikasikan dalam proyek domestik berikutnya (Lall, 1992). Meskipun Vietnam belum sepenuhnya mandiri dalam produksi kapal perang kompleks, pengalaman Molniya memberikan dasar penting untuk memperluas kemampuan galangan dalam jangka panjang.
Sektor elektronika dan sistem C4ISR menempati posisi strategis dalam model pengembangan Vietnam. Viettel High Tech menjadi ujung tombak dengan produk radar, sistem komunikasi aman, hingga wahana nirawak yang tidak hanya memenuhi kebutuhan militer domestik tetapi juga mulai dipasarkan di luar negeri. Posisi ini menunjukkan kemampuan Vietnam dalam memasuki segmen bernilai tambah tinggi yang menjadi “otak” dari sistem pertahanan modern. Dari kacamata dual-use industrialization, keunggulan Viettel di bidang 5G dan Internet of Things memperlihatkan sinergi sipil-militer yang saling memperkuat: keuntungan dari pasar sipil menopang investasi riset militer, sementara inovasi militer mendorong daya saing sektor sipil (Markowski & Hall, 2004). Dengan demikian, sektor ini mencerminkan lompatan dari sekadar follow-up learning menuju leading niche specialization.
Kunci dari keseluruhan strategi Vietnam adalah tahapan bertahap dari lisensi menuju lokalisasi dan akhirnya desain mandiri. Jalur evolutif ini sesuai dengan pola staircase model of capability development, di mana negara latecomer secara sistematis mengakumulasi keahlian melalui proyek jangkar (flagship projects). Senapan STV dan kapal Molniya berfungsi sebagai wahana pembelajaran, sementara produk radar dan UAV dari Viettel menjadi contoh capaian tahap lanjutan.
Selain faktor teknis, pameran pertahanan seperti Vietnam Defence 2024 berperan sebagai arena penting dalam strategi pengembangan kapabilitas. Pertama, ia berfungsi sebagai etalase (showcase) kemampuan domestik, yang meningkatkan kepercayaan diri industri nasional sekaligus memperkuat legitimasi politik kebijakan pertahanan. Kedua, ia menjadi instrumen diplomasi industri, mempertemukan Vietnam dengan calon mitra luar negeri untuk memperluas jaringan kerja sama. Ketiga, ia menciptakan mekanisme market signaling, di mana produk domestik diperkenalkan kepada calon pembeli dan investor, sehingga membuka peluang ekspor maupun joint development (Defense-Update, 2025). Dengan cara ini, pameran pertahanan bukan sekadar ajang pamer, melainkan bagian integral dari strategi industrialisasi pertahanan nasional.
Model pengembangan kapabilitas Vietnam memperlihatkan kombinasi dari absorptive learning, interactive learning, dan dual-use spillover. Melalui jalur bertahap dan konsistensi kebijakan, Vietnam mampu membangun basis industri pertahanan yang lebih modern dan beragam dibandingkan dua dekade sebelumnya. Meskipun masih menghadapi keterbatasan R&D frontier dan ketergantungan pada impor komponen kritis, model ini telah menempatkan Vietnam sebagai emerging defence producer dengan daya saing regional yang semakin meningkat.
Tantangan dan Keterbatasan
Meskipun menunjukkan kemajuan signifikan dalam dua dekade terakhir, industri pertahanan Vietnam tetap dibatasi oleh sejumlah kendala struktural yang khas bagi negara latecomer. Salah satu hambatan utama adalah ketergantungan pada komponen kunci berteknologi tinggi, seperti mesin kapal, sistem propulsi, sensor canggih, dan avionik. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa meskipun Vietnam mampu melakukan rekayasa ulang dan integrasi pada level menengah, ia belum sepenuhnya menguasai core technologies yang menjadi pembeda utama antara produsen berskala menengah dengan negara produsen maju. Teori technological capabilities menegaskan bahwa kapabilitas produksi tidak secara otomatis bermakna kapabilitas inovasi; untuk naik kelas, diperlukan penguasaan teknologi inti yang padat modal, padat riset, dan membutuhkan ekosistem litbang yang matang (Lall, 1992; Bell & Pavitt, 1995).
Selain itu, keterbatasan pembiayaan riset dan pengembangan (R&D) menjadi tantangan yang terus berulang. Dengan alokasi anggaran pertahanan yang masih relatif kecil dibanding negara tetangga seperti Singapura, proporsi dana yang dialokasikan khusus untuk R&D semakin terbatas. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam mengejar frontier teknologi, meskipun upaya incremental melalui proyek lisensi dan modifikasi lokal tetap berjalan. SIPRI (2022) mencatat bahwa tanpa peningkatan signifikan dalam kapasitas R&D domestik, negara-negara di Asia Tenggara berisiko terjebak pada status assembler atau system integrator tanpa bertransformasi menjadi inovator mandiri.
Dimensi lain adalah transparansi data industri. Informasi mengenai nilai ekspor, kapasitas produksi, dan kontribusi terhadap PDB pertahanan Vietnam relatif sulit diakses. Hal ini tidak hanya membatasi analisis independen, tetapi juga menurunkan daya tarik bagi investor asing yang membutuhkan kepastian informasi. Small Arms Survey (2024) menyoroti bahwa rendahnya transparansi merupakan masalah regional di Indo-Pasifik, yang berdampak pada akuntabilitas publik serta kualitas tata kelola.
Meski demikian, Vietnam berupaya merespons keterbatasan tersebut melalui instrumen hukum terbaru, yakni UU No. 38/2024/QH15. Undang-undang ini antara lain mengatur kewajiban pembangunan basis data industri pertahanan, peningkatan kapasitas R&D hingga standar global, serta mekanisme mobilisasi industri sipil untuk memperkuat resiliensi nasional. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen politik untuk mengatasi structural bottlenecks, meskipun efektivitas implementasinya masih perlu diuji dalam jangka menengah (Vietnam News, 2025).
Perbandingan dengan Indonesia
Perbandingan pengembangan industri pertahanan Vietnam dan Indonesia memperlihatkan konvergensi pada level ambisi strategis, tetapi divergensi pada tataran kelembagaan, konsistensi politik, dan pilihan sektor prioritas. Keduanya sama-sama menargetkan kemandirian pertahanan (defence self-reliance) dan pengurangan ketergantungan pada pemasok asing, suatu tema yang mengakar pada narasi kedaulatan nasional dan pengalaman sejarah panjang dalam menghadapi ancaman eksternal. Namun, Vietnam mengeksekusi ambisi tersebut melalui konsistensi politik yang terlembaga kuat, sementara Indonesia sering kali terhambat oleh fragmentasi birokrasi dan fluktuasi prioritas.
Vietnam menampilkan kesinambungan antara resolusi politik partai, instrumen hukum yang operasional, dan pelaksanaan teknis oleh badan-badan industri. Resolusi Politbiro No. 08-NQ/TW (2022) dan UU No. 38/2024/QH15 membentuk landasan institusional yang jelas, menempatkan General Department of Defence Industry (GDDI) sebagai orkestra utama, dan memastikan bahwa koordinasi lintas kementerian dipimpin langsung oleh Perdana Menteri. Sebaliknya, Indonesia meskipun telah memiliki UU No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan serta Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), masih menghadapi fragmentasi kewenangan antara Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, dan TNI sebagai pengguna utama. Fragmentasi ini memunculkan coordination failure yang mengurangi efektivitas kebijakan, ditambah dengan keterbatasan anggaran dan inkonsistensi dalam kebijakan pengadaan (Anwar, 2020; KKIP, 2023).
Perbedaan juga terlihat dalam orientasi kapabilitas. Vietnam menekankan penguasaan pada sektor elektronika militer, sistem radar, komunikasi aman, dan senjata ringan. Fokus ini tidak hanya sesuai dengan ukuran pasar domestiknya yang relatif terbatas, tetapi juga mencerminkan strategi dual-use melalui perusahaan jangkar seperti Viettel. Dengan model ini, Vietnam memperluas riset dan investasi pertahanan ke sektor sipil (telekomunikasi, 5G, IoT), sehingga tercapai skala ekonomi dan keberlanjutan finansial. Indonesia sebaliknya lebih menitikberatkan pada industri berat, seperti kapal selam, kapal perang besar, pesawat angkut, yang membutuhkan investasi modal jauh lebih besar.
Keunggulan Indonesia terlihat pada PT PAL yang telah memproduksi kapal selam kelas Chang Bogo bersama Korea Selatan serta PT Dirgantara Indonesia dengan CN-235 dan N-219. Namun, kelemahan mendasar Indonesia adalah tingginya ketergantungan pada impor komponen kritis (avionik, sensor, mesin) dan rendahnya integrasi produk antara PT PAL, PT DI, dan PT Pindad. Hal ini mencerminkan thinness of technological linkages yang membatasi sinergi intra-industri.
Instrumen diplomasi industri juga memperlihatkan perbedaan. Vietnam secara konsisten menggunakan Vietnam Defence Expo sebagai ajang untuk memamerkan produk domestik, membangun citra sebagai produsen yang kredibel, dan menarik mitra internasional dalam skema co-development. Ajang ini merupakan bagian integral dari strategi industrialisasi pertahanan Vietnam. Indonesia memang memiliki Indo Defence, tetapi pameran ini sering kali didominasi oleh vendor asing, dengan produk nasional kurang mendapat sorotan. Dengan demikian, Vietnam memposisikan pameran sebagai instrumen diplomasi industri, sementara Indonesia lebih menyerupai Arms Fair yang terbuka bagi pemasok global ketimbang sebagai etalase kapabilitas nasional.
Dalam hal mobilisasi industri nasional, Vietnam melalui UU 38/2024/QH15 telah menetapkan mekanisme mobilisasi sektor sipil untuk kebutuhan pertahanan. Basis data kapasitas industri sipil disiapkan agar dapat dimobilisasi secara cepat dalam situasi krisis. Model ini menegaskan pendekatan total defence economy di mana industri sipil menjadi bagian dari infrastruktur pertahanan negara. Indonesia sejauh ini belum memiliki sistem serupa. UU 16/2012 tidak mengatur secara eksplisit mobilisasi industri sipil, sehingga daya tahan industri pertahanan nasional dalam kondisi darurat relatif terbatas.
Indonesia memiliki kemiripan dengan Vietnam dalam hal arsitektur awal: adanya kerangka hukum nasional dan keberadaan BUMN strategis. PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia berfungsi seperti jaringan pabrik “Z” dan Viettel di Vietnam, yakni sebagai ujung tombak kapasitas domestik. Namun, hambatan utama Indonesia terletak pada fragmentasi permintaan antar matra TNI, yang menyebabkan spesifikasi beragam dan sulit distandardisasi. Akibatnya, potensi economies of scale tidak tercapai. Selain itu, inkonsistensi pembiayaan pertahanan membuat program modernisasi rentan terhenti atau mengalami penundaan. Faktor berikutnya adalah lemahnya integrasi lintas sektor: hubungan antara BUMN pertahanan, swasta nasional, universitas, dan lembaga litbang belum menghasilkan ekosistem inovasi yang kohesif.
Dari pengalaman Vietnam, terdapat empat pelajaran kunci. Pertama, konsistensi politik dan hukum harus diperkuat agar UU 16/2012 tidak berhenti sebagai norma, melainkan memiliki perangkat operasional seperti mekanisme mobilisasi industri sipil. Kedua, strategi bertahap lisensi–lokalisasi–desain mandiri perlu dimaksimalkan dengan memastikan transfer keterampilan dan intellectual property rights. Ketiga, fokus pada elektronika dan sistem C4ISR harus diperkuat karena sektor ini menentukan superioritas platform. Keempat, model dual-use seperti Viettel perlu ditiru untuk memperluas pasar dan meningkatkan keberlanjutan industri pertahanan Indonesia.
Dengan demikian, meskipun Vietnam dan Indonesia sama-sama berada dalam kategori emerging defence producers, Vietnam lebih konsisten dalam menjahit kesinambungan antara kebijakan politik, kerangka hukum, dan strategi pembelajaran teknologi. Indonesia memiliki potensi industri yang lebih besar, pasar domestik yang luas, dan sumber daya manusia yang melimpah. Namun, tanpa tata kelola yang lebih disiplin, fokus strategis pada sektor bernilai tambah tinggi, dan integrasi lintas sektor yang solid, Indonesia berisiko tetap terjebak pada tahap assembler dan tidak mampu melampaui Vietnam dalam menjadi produsen pertahanan mandiri yang kompetitif di kawasan.
Penutup
Sebagai kesimpulan, pengalaman Vietnam dalam membangun industri pertahanan menunjukkan bahwa konsistensi politik, instrumen hukum yang operasional, serta strategi bertahap merupakan fondasi penting bagi negara latecomer untuk mengejar ketertinggalan teknologi. Resolusi Politbiro dan Undang-Undang No. 38/2024/QH15 memberi kerangka institusional yang kuat, memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada level normatif, tetapi memiliki perangkat eksekusi yang jelas. Model bertahap dari lisensi, lokalisasi, hingga desain mandiri memperlihatkan bahwa industrialisasi pertahanan bukan hasil dari lompatan instan, melainkan akumulasi pembelajaran jangka panjang. Meskipun Vietnam masih menghadapi keterbatasan finansial, ketergantungan pada komponen inti, serta rendahnya transparansi, ia mampu mengompensasi kelemahan struktural tersebut dengan orientasi dual-use industry. Melalui perusahaan jangkar seperti Viettel, Vietnam berhasil menjembatani kebutuhan militer dan pasar sipil, sehingga tercipta economies of scale dan kesinambungan investasi R&D. Integrasi erat antara partai, pemerintah, dan industri domestik menjadi faktor penentu yang memperkuat lintasan catch-up industrialization.
Bagi Indonesia, pembelajaran dari Vietnam bersifat strategis. Indonesia memiliki pasar domestik yang lebih besar, sumber daya manusia yang lebih banyak, serta basis industri yang lebih beragam. Secara teoritis, potensi ini memungkinkan Indonesia untuk melampaui capaian Vietnam dan menjadi pusat industri pertahanan regional. Namun, hal itu hanya dapat terwujud jika terdapat keberanian politik untuk menegakkan koordinasi lintas sektor, memperkuat kapasitas desain dan kepemilikan hak kekayaan intelektual, serta mengembangkan ekosistem elektronika pertahanan yang terhubung dengan pasar sipil.
Adapun saran berkaitan dengan potensi Implikasi Kebijakan dapat dijabarkan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek (1–5 tahun), Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum operasional dari UU 16/2012. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi turunan yang mengatur mobilisasi industri sipil untuk kebutuhan pertahanan, pembentukan National Defence Industry Council di bawah Presiden untuk mengatasi fragmentasi kewenangan, serta kewajiban pembangunan basis data industri pertahanan. Selain itu, Indonesia perlu memfokuskan proyek utama, misalnya fregat Merah Putih, UAV menengah, dan radar nasional, sebagai wahana pembelajaran teknis. Sejalan dengan itu, ajang Indo Defence harus direposisi dari pasar senjata internasional menjadi etalase kapabilitas domestik yang menonjolkan BUMN strategis.
Dalam jangka menengah (5–10 tahun), prioritas utama adalah mencapai design authority pada platform tertentu. PT PAL harus menuntaskan transisi dari co-production menuju desain kapal perang yang sepenuhnya nasional, PT DI harus memperkuat kapabilitas UAV strategis dan pesawat angkut ringan dengan mayoritas komponen lokal, sementara PT Pindad perlu masuk ke ranah senjata pintar dan amunisi presisi. Secara paralel, ekosistem elektronika pertahanan harus ditumbuhkan dengan serius, dengan PT LEN dan konsorsium swasta-universitas sebagai pusat riset radar AESA, secure communications, dan sistem C4ISR. Pendanaan R&D minimal 2% dari anggaran pertahanan perlu dialokasikan secara berkelanjutan untuk mendukung agenda ini.
Penataan dalam jangka panjang (10–15 tahun), Indonesia ditargetkan menjadi eksportir produk pertahanan yang kompetitif di Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah. Produk unggulan yang potensial mencakup UAV, radar, kapal perang, serta senjata ringan. Pada fase ini, sistem mobilisasi industri nasional harus sudah beroperasi penuh, sehingga sektor sipil, otomotif, elektronika, energi, dapat dimobilisasi dalam krisis. Selain itu, Indonesia perlu memimpin kerja sama industri pertahanan ASEAN melalui mekanisme ADMM (ASEAN Defence Ministers’ Meeting), sehingga terbentuk integrasi regional. Posisi ini akan menempatkan Indonesia bukan hanya sebagai konsumen alutsista, tetapi juga sebagai produsen dengan daya tawar diplomatik yang lebih tinggi.
Dengan mempelajari Vietnam, Indonesia dapat memahami bahwa industrialisasi pertahanan bukan semata proyek teknis, melainkan proyek politik-ekonomi jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, koordinasi, dan keberanian berinovasi. Indonesia memiliki semua prasyarat struktural untuk melampaui capaian Vietnam, tetapi keberhasilan hanya akan diraih jika negara mampu menata kesinambungan antara kebijakan politik, perangkat hukum, strategi teknologi, dan integrasi sipil-militer. Jika prasyarat tersebut dipenuhi, Indonesia berpotensi menjadi pusat gravitasi industri pertahanan di Indo-Pasifik dan salah satu aktor utama dalam arsitektur keamanan regional.
Daftar Referensi
Anwar, D. F. (2020). Indonesia’s defence industry: Between ambition and reality (Working Paper). Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia.
Army Recognition. (2016, April 15). Vietnam launched two Project 12418 Tarantul-class corvettes produced under licence. Retrieved from https://www.armyrecognition.com
Arthur, W. B. (1989). Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events. The Economic Journal, 99(394), 116–131. https://doi.org/10.2307/2234208
Arrow, K. J. (1962). The economic implications of learning by doing. The Review of Economic Studies, 29(3), 155–173. https://doi.org/10.2307/2295952
Bell, M., & Pavitt, K. (1995). The development of technological capabilities. In I. Ul Haque (Ed.), Trade, technology, and international competitiveness (pp. 69–101). Washington, DC: The World Bank.
Bitzinger, R. A. (2003). Towards a brave new arms industry?. Oxford University Press.
Bitzinger, R. A. (2017). Defense industries in Asia: A comparative perspective. Routledge.
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128–152. https://doi.org/10.2307/2393553
Defense-Update. (2025, February 2). An overview of Vietnam Defence 2024. Retrieved from https://defense-update.com
Evans, P. (1995). Embedded autonomy: States and industrial transformation. Princeton, NJ: Princeton University Press.
GlobalSecurity.org. (n.d.). Factory Z111. Retrieved from https://www.globalsecurity.org
Hartley, K. (2007). The economics of defence policy: A new perspective. Routledge.
Johnson, C. (1982). MITI and the Japanese miracle: The growth of industrial policy, 1925–1975. Stanford University Press.
Kaplan, R. D. (2014). Asia’s cauldron: The South China Sea and the end of a stable Pacific. Random House.
KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan). (2023, March 16). Indonesia’s Committee of Defence Industries Policy, Part 1: Organization. Retrieved from https://www.kkip.go.id
Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World Development, 20(2), 165–186. https://doi.org/10.1016/0305-750X(92)90097-F
Markowski, S., & Hall, P. (2004). Defence procurement and industry policy: A small country perspective. Defence and Peace Economics, 15(2), 133–148. https://doi.org/10.1080/1024269032000110578
Matthews, R., & Maharani, D. (2019). Defence offset and the development of the Indonesian defence industry. Defence Studies, 19(2), 189–207. https://doi.org/10.1080/14702436.2019.1604986
Megginson, W. L., & Netter, J. M. (2001). From state to market: A survey of empirical studies on privatization. Journal of Economic Literature, 39(2), 321–389. https://doi.org/10.1257/jel.39.2.321
Naval News. (2025, February 11). Indonesia’s Merah Putih-class frigate: What you need to know. Retrieved from https://www.navalnews.com
Nguyen, H. T. (2020). Vietnam’s defence industry development: Drivers and prospects. Asian Security, 16(2), 143–162. https://doi.org/10.1080/14799855.2020.1718224
PR Newswire. (2025, September 3). Viettel’s high-tech military equipment makes debut at Vietnam Independence Day parade. Retrieved from https://www.prnewswire.com
Sebastian, L. C., & Gindarsah, I. (2013). Assessing Indonesia’s defence diplomacy. Defence and Security Analysis, 29(4), 292–309. https://doi.org/10.1080/14751798.2013.842710
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). (2022). Arms-production capabilities in the Indo-Pacific region. Stockholm: SIPRI. Retrieved from https://www.sipri.org
Small Arms Survey. (2024). ATT in the Indo-Pacific: Realities, challenges, and opportunities. Geneva: Small Arms Survey. Retrieved from https://www.smallarmssurvey.org
Sukma, R. (2015). Indonesia’s defence policy and regional security outlook. Australian Journal of International Affairs, 69(2), 205–220. https://doi.org/10.1080/10357718.2014.978739
Thayer, C. A. (2017). Vietnam’s defence modernisation: A regional perspective. Contemporary Southeast Asia, 39(1), 1–28. https://doi.org/10.1355/cs39-1a
The Party’s Journal. (2024, August 26). The Party’s thoughts on developing defence industry to meet the requirements of safeguarding the Fatherland. Retrieved from https://tapchiqptd.vn
Vietnam Law Magazine. (2024, July 22). New law provides particular mechanisms for national defense and security activities. Retrieved from https://vietnamlawmagazine.vn
Vietnam National Assembly. (2024, June 27). Law on Defense Industry, Security and Industrial Mobilization (Law No. 38/2024/QH15). Hanoi: National Assembly of Vietnam. Retrieved from https://bwcimplementation.org
Vietnam News. (2025, September). Vietnamese defence industry told to upgrade weapons, boost R&D to global standards. Retrieved from https://vietnamnews.vn
Viettel High Tech. (2025a). Protect to enable: A story of technology, people, and resilience that empowers defense and drives development. Retrieved from https://viettelhightech.vn
Viettel High Tech. (2025b). Protect to enable: The story of technology, people, and self-reliance. Retrieved from https://viettelhightech.vn
Leave a comment