Oleh: Bangkit Rahmat Tri Widodo
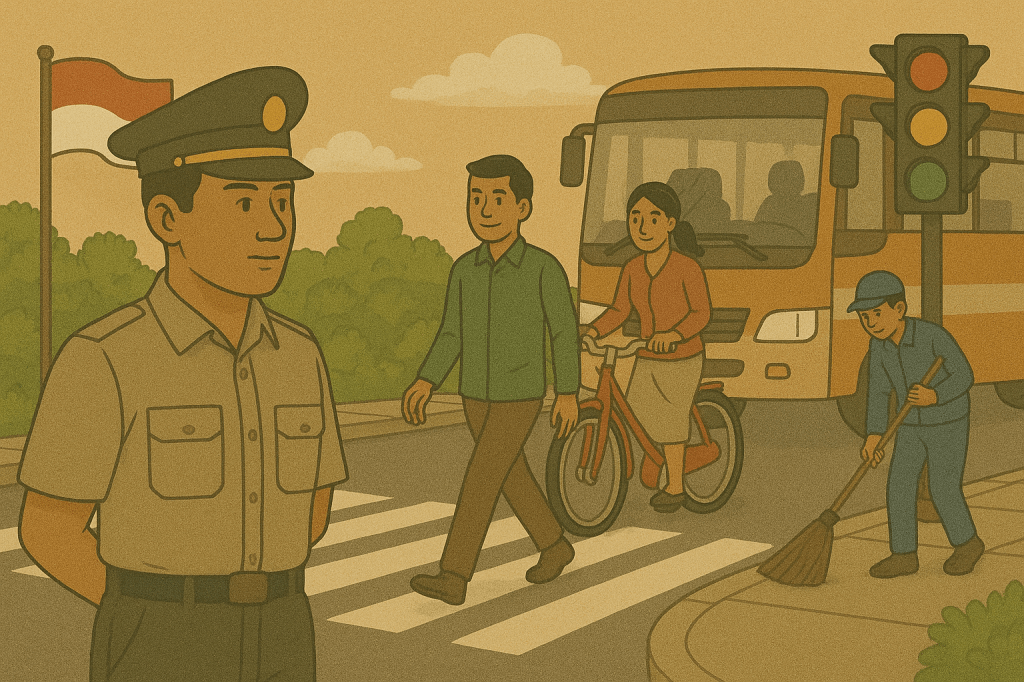
Disiplin nasional merupakan salah satu pilar fundamental bagi terwujudnya keteraturan sosial, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan daya saing bangsa dalam percaturan global. Di Indonesia, konsep disiplin nasional mengalami perjalanan historis yang dinamis, terutama ketika diletakkan dalam bingkai perubahan politik dan rezim pemerintahan. Pada masa Orde Baru, disiplin lebih banyak dipahami dalam kerangka koersif, di mana kepatuhan warga negara dipaksakan melalui kontrol negara yang ketat. Aparat negara, baik sipil maupun militer, memainkan peran dominan dalam memelihara keteraturan sosial, sehingga ruang kebebasan warga sangat terbatas. Pola disiplin semacam ini melahirkan kepatuhan yang bersifat formalistik dan artifisial, yang lebih dekat dengan authoritarian compliance ketimbang internalisasi nilai kesadaran kolektif. Paradigma pembangunanisme yang sentralistik serta represi politik menjadi fondasi dari model disiplin pada periode tersebut (Aspinall & Mietzner, 2010; Budiman, 1990).
Transisi menuju demokrasi setelah 1998 menghadirkan perubahan radikal. Euforia kebebasan membuka ruang yang luas bagi partisipasi politik, kebebasan berpendapat, serta ekspresi sosial masyarakat. Namun, perubahan ini sekaligus membawa tantangan baru yang tidak ringan. Muncul gejala melemahnya keteraturan sosial, rendahnya kepatuhan hukum, serta menurunnya kualitas civic virtue yang sesungguhnya menjadi inti dari demokrasi. Fenomena seperti meningkatnya pelanggaran aturan lalu lintas, maraknya praktik korupsi di level birokrasi, lemahnya disiplin kerja aparatur negara, dan berkurangnya penghormatan terhadap norma publik menandai adanya defisit dalam internalisasi disiplin di tingkat individu maupun kolektif (Mietzner, 2012; Liddle & Mujani, 2007).
Dalam perspektif pembangunan nasional, lemahnya disiplin berimplikasi langsung pada efektivitas kebijakan publik. Negara dengan tingkat disiplin sosial yang rendah akan menghadapi biaya ekonomi dan politik yang tinggi akibat ketidakteraturan, inefisiensi birokrasi, serta resistensi masyarakat terhadap aturan hukum. Sebaliknya, literatur mengenai social capital menegaskan bahwa masyarakat dengan tingkat disiplin publik yang tinggi cenderung memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, serta konsolidasi demokrasi yang lebih kokoh (Putnam, 1993; Fukuyama, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa disiplin tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan dan legitimasi demokrasi.
Permasalahan mendasar yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menata kembali kebijakan dan sistem disiplin nasional agar sesuai dengan prinsip demokrasi. Tantangannya terletak pada transformasi dari model disiplin yang selama ini berbasis pada pemaksaan eksternal menuju disiplin yang bersumber dari kesadaran kolektif warga negara. Disiplin demokratis harus dipahami sebagai mekanisme internalisasi nilai dan norma bersama, bukan sekadar instrumen kontrol negara. Dengan demikian, disiplin menjadi self-discipline yang lahir dari kesadaran untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepatuhan terhadap aturan publik yang menopang kepentingan bersama. Proses ini menuntut pergeseran paradigma dari obedience through coercion menuju civic discipline through awareness (Etzioni, 1995; Diamond & Morlino, 2005).
Dalam kerangka tersebut, urgensi kajian mengenai disiplin nasional di Indonesia bukan hanya terkait dengan stabilitas politik, tetapi juga dengan arah pembangunan jangka panjang. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan perumusan konseptual yang lebih kokoh mengenai disiplin demokratis, penyusunan kebijakan yang melibatkan integrasi whole of government serta partisipasi aktif whole of society, serta penyusunan roadmap jangka panjang yang mampu memberikan arah hingga 2060. Dengan cara ini, disiplin nasional dapat ditransformasikan menjadi modal sosial dan politik yang tidak hanya menopang konsolidasi demokrasi, tetapi juga mendorong Indonesia mencapai visinya sebagai negara maju dalam era global yang semakin kompetitif.
Kerangka Teori dan Konseptual
Pemahaman mengenai disiplin dalam ilmu sosial dan politik tidak pernah tunggal, melainkan berkembang sesuai dengan konteks sejarah, struktur kekuasaan, dan paradigma normatif yang digunakan. Dalam tradisi sosiologi klasik, Talcott Parsons (1951) memandang disiplin sebagai bagian dari mekanisme pengendalian sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dalam sistem masyarakat. Menurutnya, keteraturan sosial hanya dapat dipertahankan apabila individu bersedia menyesuaikan perilaku dengan seperangkat norma dan aturan yang telah dilembagakan. Dengan demikian, disiplin dipandang sebagai mekanisme integratif yang menjamin kohesi sosial melalui proses internalisasi nilai dan konformitas terhadap peran sosial.
Berbeda dengan Parsons, Michel Foucault (1977) menekankan sisi gelap dari disiplin, yaitu sebagai instrumen kekuasaan yang dapat bersifat represif. Dalam karyanya Discipline and Punish, Foucault menjelaskan bagaimana disiplin lahir sebagai bentuk “mikro-fisika kekuasaan” yang hadir dalam institusi modern seperti sekolah, penjara, dan barak militer. Melalui mekanisme pengawasan, regulasi perilaku, serta normalisasi, disiplin dipraktikkan sebagai teknologi kekuasaan yang membatasi kebebasan individu dan mengatur tubuh manusia secara sistematis. Dengan kerangka ini, disiplin bukan hanya soal keteraturan, tetapi juga bentuk kontrol politik yang dapat memperkuat dominasi negara terhadap warganya.
Dalam konteks demokrasi, kedua perspektif tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih menekankan pada dimensi civic virtue. Robert Putnam (1993), melalui studinya tentang tradisi kewargaan di Italia, menunjukkan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat social capital, yakni kepercayaan, norma, dan jaringan yang memperkuat kerja sama sosial. Disiplin, dalam kerangka ini, tidak semata lahir dari paksaan eksternal, melainkan dari nilai yang diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bagian dari etika kewargaan. Sejalan dengan itu, Amitai Etzioni (1995) menekankan pentingnya communitarianism, yaitu keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif. Bagi Etzioni, disiplin demokratis merupakan ekspresi dari tanggung jawab sosial yang diinternalisasi, sehingga warga negara bersedia membatasi kebebasannya demi menjamin kebebasan dan keteraturan bersama.
Dalam kaitannya dengan konsolidasi demokrasi, Wolfgang Merkel (2004) menegaskan bahwa demokrasi yang terkonsolidasi tidak hanya membutuhkan kerangka institusional yang kuat, tetapi juga legitimasi yang bersifat horizontal maupun vertikal. Legitimasi horizontal merujuk pada penerimaan masyarakat terhadap aturan dan nilai demokrasi, sementara legitimasi vertikal berkaitan dengan konsistensi institusi negara dalam menjalankan hukum dan kebijakan publik. Tanpa disiplin sosial yang mendukung legitimasi ganda tersebut, demokrasi cenderung rapuh dan mudah tergelincir ke dalam praktik disfungsional. Larry Diamond dan Leonardo Morlino (2005) menambahkan bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh sejauh mana warga negara berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, sekaligus sejauh mana pemerintah mampu mempertahankan akuntabilitasnya. Dalam kerangka ini, disiplin demokratis menjadi prasyarat bagi partisipasi yang sehat, karena hanya dengan kesediaan warga untuk mematuhi norma publik, ruang demokrasi dapat berfungsi secara optimal.
Untuk menata sistem disiplin nasional secara demokratis, pendekatan yang bersifat integratif mutlak diperlukan. Perspektif whole of government menawarkan kerangka untuk memastikan keterpaduan lintas kementerian, lembaga, dan tingkat pemerintahan dalam membangun budaya disiplin. Menurut Christensen dan Lægreid (2007), pendekatan ini tidak hanya menekankan koordinasi kebijakan, tetapi juga menuntut sinergi dalam implementasi agar tercapai konsistensi tata kelola publik. Namun, keterpaduan institusional semata tidak cukup. Disiplin demokratis hanya dapat bertahan apabila dilengkapi dengan pendekatan whole of society, yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat sipil, dunia pendidikan, media, dan sektor swasta. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa model collaborative governance diperlukan untuk mengintegrasikan peran negara dan masyarakat dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. Dengan cara ini, disiplin nasional tidak hanya menjadi instrumen pemerintah, tetapi juga menjadi kesepakatan kolektif yang lahir dari partisipasi luas seluruh elemen bangsa.
Dengan demikian, kerangka teori dan konseptual mengenai disiplin nasional menegaskan bahwa disiplin bukanlah konsep tunggal. Ia dapat dipahami sebagai mekanisme sosial, instrumen kekuasaan, maupun nilai kewargaan yang diinternalisasi. Dalam kerangka demokrasi Indonesia, tantangannya adalah mengelaborasi disiplin sebagai civic virtue yang menopang konsolidasi demokrasi, sekaligus memastikan bahwa penataannya dilakukan melalui tata kelola kolaboratif berbasis whole of government dan whole of society.
Disiplin Nasional dalam Konteks Indonesia
Disiplin nasional di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang kompleks, yang tampak dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan birokrasi. Dalam kehidupan sehari-hari, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas menjadi gejala yang paling kasat mata. Data Korlantas Polri menunjukkan tingginya angka pelanggaran lalu lintas, baik berupa tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, hingga mengabaikan aturan keselamatan berkendara, yang pada gilirannya berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan dan beban sosial (Setiawan, 2019). Fenomena ini menggambarkan adanya krisis kepatuhan hukum di tingkat individu, yang seharusnya menjadi indikator paling sederhana dari disiplin publik.
Masalah serupa juga terlihat dalam birokrasi. Korupsi dalam bentuk kecil atau petty corruption masih marak, mulai dari pungutan liar dalam layanan publik hingga praktik gratifikasi sehari-hari. Transparency International (2022) menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi, menunjukkan bahwa praktik korupsi di level birokrasi rendah dan menengah masih mengakar kuat. Korupsi ini bukan hanya melemahkan tata kelola, tetapi juga merusak moralitas publik, karena membentuk budaya permisif terhadap pelanggaran aturan. Lebih jauh, disiplin birokrasi sering kali rapuh. Kehadiran aparatur sipil negara yang rendah, lemahnya etos kerja, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya berbasis meritokrasi menandakan defisit disiplin institusional (Dwiyanto, 2011).
Selain itu, defisit kesadaran kolektif dalam menjaga ruang publik menjadi cermin lain dari lemahnya disiplin nasional. Perilaku membuang sampah sembarangan, perusakan fasilitas umum, hingga pelanggaran aturan lingkungan menggambarkan betapa rendahnya kesadaran warga terhadap kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin tidak hanya gagal dilembagakan di tingkat institusi negara, tetapi juga tidak berhasil diinternalisasi di tingkat masyarakat sipil.
Akar dari problematika ini dapat ditelusuri ke warisan otoritarianisme Orde Baru, di mana disiplin dipahami sebagai kepatuhan terhadap otoritas yang bersifat koersif. Pada masa itu, kepatuhan dibangun melalui pengawasan ketat negara, terutama oleh aparat keamanan, sehingga disiplin lebih dipandang sebagai bentuk obedience terhadap perintah atasan daripada civic discipline yang lahir dari kesadaran warga negara (Aspinall & Mietzner, 2010). Pola tersebut menghasilkan budaya kepatuhan formalistik, namun tidak menumbuhkan internalisasi nilai disiplin dalam masyarakat.
Paska-1998, transisi menuju demokrasi membawa euforia kebebasan yang besar. Ruang publik yang sebelumnya dibatasi kini terbuka, memungkinkan tumbuhnya partisipasi politik dan ekspresi sosial yang lebih luas. Akan tetapi, kebebasan ini juga memunculkan fenomena democratic disarray, di mana keteraturan sosial menjadi rapuh karena kurangnya disiplin kolektif. Kebebasan sering kali ditafsirkan sebagai kebebasan tanpa batas, sehingga muncul paradoks antara tuntutan kebebasan individu dan kepentingan untuk menjaga ketertiban sosial (Mietzner, 2012; Heryanto & Hadiz, 2005).
Selain faktor struktural dan politik, lemahnya pendidikan karakter dan civic education turut menjadi penyebab mendasar. Kurikulum pendidikan nasional lebih banyak menekankan aspek kognitif dan akademik, sementara pembentukan watak kewargaan dan disiplin kolektif kurang mendapat perhatian serius. Lickona (1991) menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan instrumen utama dalam membentuk civic virtue, yakni kesediaan warga negara untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan tanggung jawab sosial. Tanpa pendidikan yang menanamkan nilai kedisiplinan sejak dini, masyarakat akan sulit mengembangkan sikap disiplin yang lahir dari kesadaran, bukan paksaan.
Kondisi ini menegaskan urgensi penataan ulang konsep disiplin nasional di Indonesia. Tanpa disiplin yang demokratis, sulit membayangkan Indonesia dapat mencapai visinya menjadi negara maju pada 2045, sebagaimana dicanangkan dalam Visi Indonesia Emas. Negara dengan disiplin sosial yang rapuh akan menghadapi biaya pembangunan yang lebih tinggi, baik karena inefisiensi birokrasi, ketidakpatuhan hukum, maupun lemahnya kohesi sosial. Sebaliknya, apabila disiplin dapat ditransformasikan menjadi kesadaran kolektif yang demokratis, maka ia akan menjadi modal sosial yang memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan memastikan legitimasi demokrasi tetap kokoh. Dengan demikian, pembangunan disiplin nasional tidak lagi dapat dipandang sebagai agenda tambahan, melainkan sebagai syarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Strategi Penataan Kebijakan Disiplin Nasional
Penataan kebijakan disiplin nasional di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berlapis, karena disiplin bukanlah konsep tunggal yang dapat dipaksakan dari atas ke bawah, melainkan sebuah sistem nilai dan praktik sosial yang perlu diharmonisasikan dengan prinsip demokrasi. Strategi ini dapat dipahami melalui lima dimensi utama, yakni normatif, edukatif, institusional, sosial-kultural, dan teknologi, yang saling berkaitan dan harus dijalankan secara simultan.
Dimensi normatif menjadi fondasi utama karena menyangkut kerangka hukum dan regulasi yang melandasi implementasi disiplin nasional. Harmonisasi regulasi dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sangat penting agar disiplin tidak dipahami sebagai alat represi negara, melainkan sebagai mekanisme untuk menjamin keteraturan sosial yang adil dan setara. Studi tentang hukum tata negara menunjukkan bahwa legitimasi sebuah aturan tidak hanya ditentukan oleh proses legislasi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut (Habermas, 1996). Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa regulasi tentang disiplin, baik di sektor birokrasi, pendidikan, maupun ruang publik, harus selalu diletakkan dalam kerangka negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan individu sekaligus menjaga kepentingan kolektif (Asshiddiqie, 2005).
Dimensi edukatif menekankan pentingnya penguatan kurikulum pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter. Pendidikan merupakan arena utama dalam membentuk kesadaran disiplin sejak dini. Thomas Lickona (1991) berpendapat bahwa pendidikan karakter tidak sekadar menanamkan pengetahuan moral, tetapi juga membentuk kebiasaan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, civic education yang dikembangkan di sekolah-sekolah harus diperkuat agar mampu menumbuhkan civic virtue, yakni kesediaan warga negara untuk mengorbankan sebagian kebebasan individu demi kepentingan bersama (Putnam, 1993). Dengan cara ini, disiplin dapat ditransformasikan dari kepatuhan yang dipaksakan menjadi kepatuhan yang lahir dari kesadaran moral dan intelektual.
Dimensi institusional berkaitan dengan tata kelola birokrasi dan lembaga negara. Birokrasi yang tidak disiplin akan sulit menanamkan nilai disiplin kepada masyarakat. Reformasi birokrasi dengan menekankan meritokrasi, transparansi, serta penerapan sistem reward and punishment yang konsisten merupakan keharusan. Studi Dwiyanto (2011) menegaskan bahwa birokrasi di Indonesia masih sering terjebak pada budaya patrimonialisme dan patronase, sehingga melemahkan integritas institusi. Melalui penerapan merit system dan sistem evaluasi kinerja yang terukur, disiplin institusional dapat diperkuat dan memberi teladan bagi masyarakat. Lebih jauh, lembaga negara seperti TNI, Polri, dan ASN dapat berfungsi sebagai role model dalam menanamkan disiplin demokratis yang tidak otoriter, tetapi tetap tegas, konsisten, dan akuntabel.
Dimensi sosial-kultural menekankan bahwa disiplin tidak hanya dapat dibangun melalui regulasi dan institusi, melainkan juga melalui internalisasi nilai di ruang publik. Disiplin kolektif harus diciptakan sebagai budaya yang hidup dalam masyarakat, dan hal ini membutuhkan partisipasi komunitas, media, serta pemanfaatan ruang publik digital. Inglehart dan Welzel (2005) menjelaskan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan dalam masyarakat modern terbentuk melalui interaksi sosial yang berkelanjutan, baik dalam lingkup keluarga, komunitas lokal, maupun media massa. Dalam konteks Indonesia, membangun budaya disiplin publik dapat dilakukan dengan mendorong komunitas sipil untuk menjadi penggerak utama gerakan kesadaran sosial, sekaligus memanfaatkan media arus utama dan media sosial untuk membangun opini publik positif tentang pentingnya kedisiplinan dalam demokrasi. Dengan demikian, disiplin tidak lagi dipandang sebagai kewajiban yang dipaksakan, melainkan sebagai identitas kolektif yang membanggakan.
Dimensi teknologi menjadi unsur baru yang semakin penting dalam era digital. Sistem monitoring kepatuhan berbasis teknologi dapat menjadi instrumen efektif untuk mendukung penegakan disiplin yang transparan dan akuntabel. Konsep open government data yang berkembang sejak awal 2010-an menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi warga negara (Janssen et al., 2012). Melalui sistem digital, masyarakat tidak hanya dapat dimonitor dalam hal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dapat terlibat langsung dalam proses pengawasan. Misalnya, aplikasi pelaporan publik berbasis digital dapat memfasilitasi warga untuk melaporkan pelanggaran aturan secara langsung, sementara pemerintah dapat menggunakan big data analytics untuk mengidentifikasi pola ketidakpatuhan yang sistemik. Integrasi teknologi semacam ini akan memperkuat kapasitas negara dalam menegakkan disiplin, sekaligus memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses tersebut.
Dengan menggabungkan dimensi normatif, edukatif, institusional, sosial-kultural, dan teknologi, strategi penataan kebijakan disiplin nasional dapat diarahkan untuk membangun sistem disiplin yang demokratis, berkelanjutan, dan adaptif. Disiplin yang kokoh tidak akan lahir dari satu dimensi saja, tetapi dari keterpaduan berbagai aspek yang saling memperkuat. Hanya dengan cara demikian, disiplin dapat menjadi modal sosial dan politik yang menopang konsolidasi demokrasi sekaligus mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Roadmap dan Timeline
2025–2030: Fondasi Normatif dan Kultural
Tahap awal pembangunan disiplin nasional yang demokratis di Indonesia pada periode 2025 hingga 2030 perlu difokuskan pada pembentukan fondasi normatif dan kultural yang kokoh. Periode ini dapat dipahami sebagai fase penyiapan kerangka hukum, nilai, dan budaya yang akan menopang pembangunan disiplin nasional jangka panjang. Tanpa kerangka normatif yang jelas dan internalisasi nilai di tingkat masyarakat, setiap kebijakan disiplin berpotensi kembali jatuh ke dalam jebakan koersivitas yang identik dengan masa otoritarian, sehingga kehilangan legitimasi sosial dan politiknya.
Langkah pertama yang menjadi prioritas adalah penyusunan Undang-Undang Sistem Disiplin Nasional. Regulasi khusus yang menempatkan disiplin sebagai instrumen pembangunan demokratis akan menjadi payung hukum yang menjamin konsistensi kebijakan lintas sektor. Dalam perspektif teori hukum demokratis, Habermas (1996) menegaskan bahwa legitimasi hukum hanya dapat diperoleh melalui proses deliberatif yang partisipatif, di mana hukum dipandang sah bukan semata karena diproduksi oleh lembaga negara, melainkan karena lahir dari konsensus publik. Oleh karena itu, penyusunan undang-undang ini perlu dilakukan dengan melibatkan tidak hanya pemerintah dan parlemen, tetapi juga masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok profesi, agar hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi kolektif bangsa. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa perumusan kerangka hukum yang inklusif akan meningkatkan kepatuhan sosial karena warga merasa memiliki keterikatan moral terhadap aturan yang disepakati bersama (Tyler, 2006).
Selain penguatan kerangka normatif, dimensi kultural menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pada fase ini, integrasi civic education ke dalam semua level pendidikan harus menjadi prioritas strategis. Civic education bukan hanya instrumen untuk mentransfer pengetahuan tentang konstitusi atau hak-hak politik warga negara, melainkan sarana untuk membentuk civic virtue, yakni kebiasaan kewarganegaraan yang menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab kolektif (Diamond & Morlino, 2005). Putnam (1993) dalam penelitiannya tentang Italia menegaskan bahwa keberhasilan institusi demokrasi bergantung pada seberapa dalam nilai kewarganegaraan tertanam dalam masyarakat. Dengan memperkuat pendidikan kewargaan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Indonesia dapat menumbuhkan generasi baru yang memahami disiplin bukan sebagai kewajiban eksternal, tetapi sebagai kesadaran intrinsik untuk menjaga keteraturan sosial.
Integrasi civic education harus pula dilengkapi dengan pendidikan karakter yang sistematis. Thomas Lickona (1991) menekankan bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk bukan hanya pikiran, tetapi juga hati dan perilaku. Dalam konteks disiplin nasional, hal ini berarti pendidikan harus menanamkan nilai tanggung jawab, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan bersama sebagai bagian dari identitas kewarganegaraan. Kurikulum perlu diarahkan agar mampu menghubungkan antara disiplin individu, keteraturan sosial, dan kemajuan bangsa. Hal ini sejalan dengan pandangan Etzioni (1995) tentang communitarianism, di mana kebebasan individu selalu harus diimbangi dengan tanggung jawab kolektif terhadap masyarakat.
Sejalan dengan pembangunan kerangka normatif dan penguatan pendidikan, pemerintah juga perlu meluncurkan sebuah kampanye nasional yang berfungsi sebagai instrumen kultural untuk membangun kesadaran bersama. Sebuah kampanye bertajuk “Disiplin Demokratis, Indonesia Maju” dapat dijadikan narasi kolektif untuk memperkuat imajinasi sosial bangsa. Studi tentang komunikasi politik menunjukkan bahwa kampanye publik mampu membentuk agenda kognitif masyarakat dengan mengubah cara warga memandang isu tertentu (McCombs & Shaw, 1972). Melalui kampanye ini, disiplin dapat diposisikan bukan sekadar sebagai kewajiban, melainkan sebagai modal kemajuan yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Dengan dukungan media massa, media sosial, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal, kampanye ini dapat menciptakan social norm baru di mana disiplin dipersepsikan sebagai kebanggaan nasional, bukan sekadar aturan yang harus ditaati.
Seluruh langkah tersebut, yakni pembentukan kerangka hukum melalui Undang-Undang Sistem Disiplin Nasional, penguatan civic education dan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan, serta pelaksanaan kampanye nasional yang membangun kesadaran kolektif, merupakan bagian dari fase fondasional dalam pembangunan disiplin nasional demokratis. Tanpa fondasi ini, setiap upaya pembangunan disiplin akan rapuh dan rentan dipersepsikan sebagai instrumen koersif belaka. Namun dengan fondasi normatif dan kultural yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menanamkan disiplin sebagai civic virtue yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai prasyarat bagi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
2030–2040: Institusionalisasi dan Penguatan Kapasitas
Dekade 2030 hingga 2040 dapat dipahami sebagai fase institusionalisasi, yaitu tahap di mana fondasi normatif dan kultural yang dibangun sebelumnya mulai dilembagakan ke dalam sistem pemerintahan dan tata kelola masyarakat secara lebih struktural. Pada tahap ini, strategi penataan disiplin nasional tidak lagi berfokus pada pembentukan kerangka hukum dan kesadaran dasar, melainkan pada penguatan kapasitas institusi agar disiplin benar-benar terintegrasi dalam praktik birokrasi, sistem politik, dan kehidupan sosial sehari-hari.
Salah satu prioritas utama dalam fase ini adalah implementasi sistem pemerintahan digital yang dirancang untuk mendukung tata kelola disiplin di kalangan aparatur negara, baik di tingkat aparatur sipil negara, TNI, maupun Polri. Transformasi digital dalam pemerintahan bukan sekadar persoalan modernisasi teknologi, melainkan sebuah paradigma baru yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam manajemen publik (Margetts & Dunleavy, 2013). Dengan digital governance, berbagai aspek kedisiplinan aparatur dapat dipantau secara real-time melalui sistem informasi kinerja, absensi elektronik, dan evaluasi berbasis data besar (big data analytics). Lebih jauh, pemanfaatan teknologi ini memungkinkan negara mengurangi discretionary power yang seringkali menjadi pintu masuk bagi praktik penyalahgunaan wewenang, sekaligus menutup ruang bagi perilaku indisipliner yang selama ini sulit dikendalikan. Pengalaman Estonia sebagai salah satu negara dengan tata kelola digital terbaik menunjukkan bahwa integrasi digital governance mampu menekan praktik korupsi sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Drechsler, 2018).
Selain penguatan sistem digital, fase institusionalisasi juga harus diarahkan pada penataan sistem meritokrasi dalam rekrutmen dan pengelolaan aparatur negara. Selama beberapa dekade, birokrasi di Indonesia kerap diwarnai oleh praktik patronase, nepotisme, dan jual beli jabatan, yang melemahkan kualitas institusi dan memperburuk kedisiplinan kerja (Dwiyanto, 2011). Meritokrasi menekankan bahwa rekrutmen, promosi, dan penempatan aparatur harus berbasis pada kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan pada kedekatan politik maupun hubungan personal. Teori administrasi publik menegaskan bahwa merit system merupakan salah satu pilar utama tata kelola modern, karena hanya dengan birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik patronase, negara dapat menghadirkan layanan publik yang efektif (Peters & Pierre, 2012). Dengan penerapan meritokrasi yang konsisten, Indonesia tidak hanya membangun disiplin birokrasi, tetapi juga menciptakan insentif struktural yang mendorong aparatur untuk bekerja dengan penuh integritas. Hal ini akan memperkuat keteladanan birokrasi sebagai contoh nyata dari disiplin demokratis yang dapat diikuti oleh masyarakat.
Namun, institusionalisasi disiplin nasional tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada negara. Masyarakat sipil harus diberi ruang yang lebih luas untuk mengawasi dan sekaligus memperkuat budaya disiplin sosial. Civil society organizations (CSO) memainkan peran penting sebagai penyeimbang kekuasaan, karena melalui mekanisme watchdog, mereka dapat memastikan bahwa disiplin tidak dipraktikkan secara represif, tetapi tetap selaras dengan prinsip demokrasi (Diamond, 1999). Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya collaborative governance di mana negara dan masyarakat sipil bekerja bersama dalam merumuskan dan mengawasi implementasi kebijakan. Dalam konteks disiplin nasional, CSO dapat terlibat dalam kampanye publik, advokasi kebijakan, hingga pengawasan langsung terhadap praktik birokrasi dan aparat penegak hukum. Kehadiran masyarakat sipil dalam fungsi pengawasan juga dapat mencegah negara terjebak dalam pendekatan koersif yang berlawanan dengan nilai demokrasi.
Dekade institusionalisasi ini dengan demikian menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang pembangunan disiplin nasional. Implementasi digital governance akan memastikan bahwa disiplin aparatur negara dapat dipantau secara obyektif dan transparan, sistem meritokrasi akan menutup ruang bagi praktik patronase yang melemahkan birokrasi, sementara keterlibatan masyarakat sipil akan menjamin bahwa disiplin tetap menjadi civic virtue yang diinternalisasi, bukan instrumen represi. Apabila ketiga pilar ini dapat ditegakkan secara konsisten, maka disiplin nasional pada periode 2030–2040 tidak hanya akan menjadi kebijakan negara, tetapi juga sebuah sistem sosial yang melekat dalam praktik keseharian bangsa Indonesia.
2040–2050: Konsolidasi dan Transformasi Sosial
Dekade 2040 hingga 2050 merupakan fase konsolidasi, yakni periode di mana disiplin nasional yang sebelumnya telah dilembagakan dalam kerangka hukum, budaya, dan institusi harus diperkokoh sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional dan strategi global Indonesia. Pada tahap ini, disiplin tidak lagi dipandang semata sebagai instrumen sosial domestik, tetapi sebagai modal pembangunan jangka panjang yang menopang keberhasilan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dan agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
Integrasi disiplin sebagai pilar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045 merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditawar. RPJPN sebagai dokumen pembangunan makro yang menjadi pedoman negara selama dua dekade harus memuat disiplin nasional bukan hanya sebagai nilai kultural, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan lintas sektor. Disiplin dapat diletakkan sebagai cross-cutting issue yang memengaruhi efektivitas kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertahanan, maupun lingkungan. Dalam literatur kebijakan publik, isu-isu lintas sektor seperti disiplin perlu dilembagakan secara eksplisit agar memiliki daya ikat terhadap seluruh institusi pemerintahan (Howlett & Cashore, 2014). Dengan menjadikan disiplin sebagai pilar RPJPN, Indonesia memastikan bahwa keteraturan sosial dan tata kelola publik yang konsisten akan menjadi fondasi bagi keberhasilan pembangunan jangka panjang.
Sejalan dengan RPJPN, disiplin nasional juga harus diposisikan sebagai bagian dari agenda pencapaian SDGs Indonesia. Agenda global ini menekankan keterkaitan antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan (United Nations, 2015). Disiplin memiliki relevansi langsung dengan sejumlah tujuan, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan institusi yang efektif, dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Negara dengan tingkat disiplin sosial yang tinggi akan lebih mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan, menekan angka ketidakpatuhan hukum, dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, disiplin nasional dapat dipandang sebagai enabling factor dalam mencapai keberhasilan SDGs secara menyeluruh.
Untuk memastikan konsistensi implementasi, perlu diciptakan sebuah indikator nasional yang dapat mengukur kualitas disiplin publik secara obyektif. Indikator ini dapat dirumuskan dalam bentuk Civic Discipline Index (CDI), yang berfungsi sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana disiplin telah terinternalisasi di berbagai lapisan masyarakat. CDI dapat mengukur variabel-variabel seperti kepatuhan hukum, integritas birokrasi, partisipasi warga dalam menjaga ruang publik, serta komitmen masyarakat terhadap norma kolektif. Model serupa telah banyak digunakan dalam mengukur kualitas demokrasi dan tata kelola, seperti Worldwide Governance Indicators oleh Bank Dunia (Kaufmann et al., 2010) atau Rule of Law Index yang diterbitkan oleh World Justice Project (2019). Dengan adanya CDI, pemerintah dan masyarakat dapat memiliki alat evaluasi yang sistematis untuk menilai keberhasilan maupun kelemahan dalam membangun disiplin nasional. Lebih jauh, CDI dapat menjadi instrumen komparatif yang memungkinkan Indonesia menempatkan dirinya dalam peta global mengenai kedisiplinan sosial dan tata kelola demokratis.
Disiplin yang terkonsolidasi pada dekade ini juga harus diposisikan sebagai sumber daya strategis bagi daya saing global Indonesia. Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy), riset dan teknologi menjadi faktor penentu kemajuan bangsa. Namun, riset dan teknologi tidak akan berkembang optimal tanpa adanya disiplin yang kuat, baik dalam manajemen institusi, praktik penelitian, maupun etika akademik. Negara-negara maju menunjukkan bahwa kedisiplinan dalam riset dan inovasi mendorong terciptanya ekosistem yang produktif, transparan, dan kompetitif (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Di bidang ekonomi, disiplin memainkan peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang stabil, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap kredibilitas institusi domestik (North, 1990). Sementara itu, dalam ranah teknologi, disiplin dalam tata kelola data, perlindungan privasi, dan regulasi etis akan menentukan sejauh mana Indonesia dapat bersaing di pasar digital global.
Dengan menjadikan disiplin sebagai bagian dari daya saing global, Indonesia tidak hanya memperkuat fondasi domestiknya, tetapi juga membangun reputasi internasional sebagai negara demokratis yang stabil, tertib, dan inovatif. Hal ini akan memberi Indonesia posisi tawar yang lebih kuat dalam kerja sama internasional, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun keamanan. Dengan demikian, dekade 2040–2050 merupakan periode strategis untuk memastikan bahwa disiplin nasional tidak hanya melekat dalam ruang domestik, tetapi juga menjadi identitas yang menegaskan kapasitas Indonesia sebagai aktor penting dalam tatanan global multipolar.
2050–2060: Disiplin sebagai Modal Peradaban
Memasuki dekade 2050 hingga 2060, disiplin nasional yang sebelumnya telah dibangun melalui fondasi normatif, internalisasi kultural, dan institusionalisasi yang berkelanjutan, harus mencapai fase tertingginya, yakni transformasi menjadi modal peradaban bangsa. Pada tahap ini, disiplin tidak lagi dipandang sebatas mekanisme sosial atau instrumen tata kelola, melainkan telah menjelma menjadi nilai bersama (shared value) yang menjadi identitas kolektif bangsa Indonesia. Seperti halnya nilai gotong royong yang selama ini dipandang sebagai etos sosial, disiplin yang demokratis dapat berfungsi sebagai norma dasar yang menuntun perilaku warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, maupun budaya.
Menjadikan disiplin sebagai nilai bersama menuntut lebih dari sekadar regulasi dan institusionalisasi. Ia memerlukan internalisasi lintas generasi sehingga tumbuh sebagai habitus sosial dalam pengertian Pierre Bourdieu (1977), yakni sistem disposisi yang tertanam dalam individu dan kolektif, yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan merasakan. Apabila pada tahap-tahap awal disiplin masih membutuhkan dorongan regulatif dan insentif birokratis, maka pada periode ini disiplin akan berfungsi secara otomatis sebagai norma sosial yang tidak diperdebatkan lagi, melainkan diterima sebagai standar moral bersama. Dengan demikian, disiplin menjadi bagian dari peradaban bangsa, yang menopang keberlanjutan pembangunan sekaligus memperkokoh identitas nasional di era global.
Keberhasilan menginternalisasi disiplin sebagai nilai peradaban juga akan menempatkan Indonesia sebagai model disiplin demokratis di kawasan Asia Tenggara. Selama beberapa dekade, negara-negara di kawasan ini menghadapi dilema antara stabilitas politik dan kebebasan demokratis. Beberapa negara menekankan keteraturan dengan mengorbankan kebebasan, sementara yang lain menekankan kebebasan dengan mengabaikan keteraturan. Apabila Indonesia berhasil menunjukkan bahwa disiplin dapat dibangun tanpa represi, tetapi melalui kesadaran kolektif dalam kerangka demokrasi, maka Indonesia akan menawarkan model alternatif yang relevan bagi negara-negara berkembang lainnya. Model ini akan menegaskan bahwa disiplin dan demokrasi bukanlah dua konsep yang saling bertentangan, melainkan dapat saling menopang untuk menciptakan tata kelola yang stabil sekaligus inklusif (Merkel, 2004; Diamond, 1999).
Posisi Indonesia sebagai model disiplin demokratis akan memperkuat perannya dalam kepemimpinan regional dan global. Dalam perspektif teori hubungan internasional, soft power menjadi instrumen penting bagi kepemimpinan global, karena memengaruhi negara lain bukan melalui paksaan militer atau tekanan ekonomi, melainkan melalui daya tarik nilai, budaya, dan legitimasi moral (Nye, 2004). Disiplin demokratis yang menjadi nilai bersama bangsa Indonesia akan berfungsi sebagai soft power baru, karena menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola kebebasan sekaligus menjaga keteraturan dalam kerangka demokrasi. Dengan reputasi ini, Indonesia akan memiliki kredibilitas lebih besar dalam forum-forum internasional, baik di ASEAN, G20, maupun PBB, sekaligus memperluas peranannya dalam menciptakan tata dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.
Lebih jauh, disiplin sebagai modal peradaban juga akan menopang kepemimpinan global Indonesia dalam bidang-bidang strategis seperti ekonomi digital, riset sains dan teknologi, serta tata kelola iklim dan lingkungan. Negara dengan disiplin sosial yang tinggi akan lebih mampu mengelola kompleksitas pembangunan global, mulai dari transformasi energi, transisi digital, hingga kerja sama keamanan lintas negara. Dalam kerangka global multipolar yang sarat ketidakpastian, keunggulan suatu bangsa tidak hanya diukur dari kapasitas material, tetapi juga dari kohesi sosial dan konsistensi nilai yang menopang daya tahan (resilience) nasional (Acharya, 2014). Disiplin yang demokratis akan memperkuat resilience Indonesia, menjadikannya bangsa yang mampu menghadapi disrupsi global tanpa kehilangan jati diri, sekaligus memberikan inspirasi bagi negara lain yang tengah mencari keseimbangan antara keteraturan sosial dan kebebasan demokratis.
Dengan demikian, periode 2050 hingga 2060 merupakan puncak dari proses panjang pembangunan disiplin nasional. Pada tahap ini, disiplin telah melewati fase normatif, edukatif, institusional, dan konsolidasi, hingga akhirnya melekat sebagai modal peradaban bangsa. Disiplin yang demokratis akan menjadi identitas kolektif Indonesia, menjadikan negara ini model disiplin demokratis di kawasan, serta menopang kepemimpinan global Indonesia melalui daya tarik nilai dan kredibilitas moral. Transformasi ini menunjukkan bahwa disiplin tidak hanya soal kepatuhan, melainkan tentang peradaban: bagaimana sebuah bangsa mengatur dirinya dengan sadar, konsisten, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama dan kontribusi terhadap dunia.
Indikator Pengukuran Kualitas Disiplin Nasional
Pengukuran kualitas disiplin nasional merupakan tahap krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan tidak berhenti pada level normatif dan institusional, tetapi dapat dievaluasi secara obyektif melalui instrumen yang terukur. Dalam literatur kebijakan publik, indikator dianggap sebagai policy instrument yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang efektivitas implementasi, sekaligus memfasilitasi pengambilan keputusan yang berbasis bukti (Marradi, 1990). Tanpa indikator yang jelas, disiplin nasional berisiko menjadi jargon politik semata tanpa pijakan empiris. Oleh karena itu, dibutuhkan seperangkat instrumen evaluasi yang mampu menangkap kompleksitas disiplin sebagai fenomena multidimensional, yang mencakup aspek individual, institusional, dan struktural.
Civic Discipline Index (CDI) dirancang sebagai indikator utama yang mengukur tingkat partisipasi warga negara dalam mematuhi norma publik. Indeks ini berfokus pada dimensi disiplin sosial, misalnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, serta keterlibatan dalam menjaga fasilitas umum. Putnam (1993) menegaskan bahwa keteraturan sosial yang lahir dari civic virtue merupakan fondasi bagi demokrasi yang berkualitas, karena warga negara yang disiplin akan lebih mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Dengan CDI, negara dapat menilai sejauh mana nilai disiplin telah terinternalisasi sebagai kebiasaan sosial, bukan sekadar kepatuhan yang dipaksakan. Indeks ini juga dapat berfungsi sebagai alat komparatif antarwilayah, sehingga pemerintah daerah dapat dievaluasi berdasarkan keberhasilan mereka dalam menumbuhkan budaya disiplin warganya.
Public Integrity Index berfungsi sebagai ukuran kepatuhan birokrasi dan pejabat publik terhadap standar integritas. Disiplin di tingkat birokrasi memiliki dampak langsung terhadap kredibilitas negara di mata masyarakat. Apabila birokrasi lemah dalam menegakkan aturan internal dan masih terjebak dalam praktik korupsi, maka sulit membayangkan masyarakat luas akan meneladani perilaku disiplin. Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2010) dalam kajian Worldwide Governance Indicators menunjukkan bahwa integritas birokrasi berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Indeks integritas semacam ini dapat mengukur variabel seperti kepatuhan terhadap aturan kepegawaian, ketepatan waktu, transparansi dalam penggunaan anggaran, dan ketiadaan praktik patronase. Dengan adanya Public Integrity Index, disiplin di kalangan aparatur negara dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara lebih sistematis.
Rule of Law Index berperan sebagai instrumen untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Disiplin nasional tidak dapat berkembang tanpa kepastian hukum yang konsisten dan adil. World Justice Project (2019) menegaskan bahwa rule of law merupakan fondasi bagi terciptanya keteraturan sosial, karena hanya dengan hukum yang ditegakkan secara non-diskriminatif masyarakat akan terdorong untuk bersikap patuh. Indeks ini dapat menilai berbagai dimensi, mulai dari akses terhadap keadilan, independensi peradilan, hingga efektivitas aparat penegak hukum. Apabila hukum ditegakkan secara selektif atau menjadi instrumen politik, maka disiplin masyarakat akan melemah karena hilangnya legitimasi norma publik. Oleh karena itu, Rule of Law Index berfungsi sebagai penghubung antara disiplin demokratis dan konsolidasi negara hukum.
Open Government Index melengkapi indikator-indikator sebelumnya dengan menilai transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Disiplin yang demokratis hanya dapat ditegakkan apabila masyarakat memiliki akses terhadap informasi publik dan ruang partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Janssen, Charalabidis, dan Zuiderwijk (2012) menjelaskan bahwa open government data memperkuat akuntabilitas pemerintah sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan. Dengan adanya Open Government Index, dapat diukur sejauh mana masyarakat sipil terlibat dalam mengawasi praktik birokrasi, melaporkan pelanggaran, dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Indeks ini juga penting untuk mencegah disiplin dipraktikkan secara koersif, karena keterbukaan dan partisipasi publik berfungsi sebagai pengaman demokratis.
Global Competitiveness Index (GCI) yang dikembangkan oleh World Economic Forum menambahkan dimensi internasional dalam pengukuran disiplin nasional. Disiplin bukan hanya soal kepatuhan domestik, tetapi juga faktor yang menentukan daya saing global. Schwab (2019) menegaskan bahwa negara dengan tingkat disiplin publik yang tinggi, birokrasi yang bersih, serta sistem hukum yang transparan akan lebih kompetitif dalam menarik investasi, mengembangkan inovasi, dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Dalam konteks Indonesia, disiplin dapat menjadi intangible capital yang memperkuat daya saing di bidang riset, teknologi, dan industri. Dengan GCI, kontribusi disiplin terhadap posisi Indonesia dalam ekonomi global dapat dipantau, sekaligus menjadi alat untuk menilai sejauh mana pembangunan disiplin nasional memberikan dampak nyata terhadap daya saing internasional.
Dengan adanya kombinasi lima indikator tersebut, pengukuran kualitas disiplin nasional dapat mencakup seluruh aspek penting: kesadaran masyarakat, integritas birokrasi, efektivitas hukum, transparansi pemerintahan, dan daya saing global. Kombinasi ini menjadikan disiplin tidak hanya diukur secara normatif, tetapi juga secara empiris melalui data kuantitatif dan kualitatif yang dapat diverifikasi. Lebih dari itu, sistem indikator ini memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama mengevaluasi capaian, mengidentifikasi kelemahan, dan merumuskan kebijakan korektif. Dengan demikian, disiplin nasional benar-benar dapat diposisikan sebagai civic virtue yang terukur, terpantau, dan terintegrasi dalam pembangunan demokratis menuju Indonesia Emas 2045 dan kepemimpinan global pada 2060.
Penutup
Disiplin nasional dalam konteks Indonesia tidak dapat lagi dipahami sekadar sebagai instrumen koersif negara untuk memaksakan kepatuhan warga. Pengalaman masa Orde Baru menunjukkan bahwa disiplin yang dibangun di atas kontrol represif hanya melahirkan kepatuhan formalistik tanpa internalisasi nilai kewargaan (Aspinall & Mietzner, 2010). Transisi demokrasi pasca-1998 membuka ruang kebebasan politik dan sosial, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa democratic disarray, yang ditandai dengan rendahnya kepatuhan hukum, maraknya korupsi kecil, lemahnya disiplin birokrasi, serta defisit kesadaran kolektif dalam menjaga ruang publik (Mietzner, 2012).
Dalam konteks pembangunan bangsa, disiplin memiliki kedudukan yang sangat strategis. Ia merupakan prasyarat bagi keteraturan sosial, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta daya saing global. Disiplin yang demokratis harus dimaknai sebagai civic virtue, yakni kesediaan warga negara untuk membatasi kebebasan individunya demi menjaga kepentingan kolektif, sekaligus menjamin berfungsinya institusi demokratis (Putnam, 1993; Etzioni, 1995). Dengan demikian, disiplin tidak hanya menjadi fondasi konsolidasi demokrasi, tetapi juga modal sosial yang menentukan arah pembangunan jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.
Untuk mewujudkan disiplin nasional yang demokratis, kerangka teori dan konseptual telah menunjukkan pentingnya transisi dari disiplin sebagai social control menuju disiplin sebagai internalized value. Parsons (1951) melihat disiplin sebagai mekanisme integratif yang menopang keteraturan, sementara Foucault (1977) memperingatkan bahaya disiplin sebagai instrumen kekuasaan represif. Perspektif Putnam (1993) dan Etzioni (1995) memberikan jalan tengah dengan menempatkan disiplin dalam ranah civic virtue yang tumbuh dari tanggung jawab sosial warga negara. Dalam kerangka demokrasi, disiplin juga harus dilembagakan melalui legitimasi horizontal masyarakat dan legitimasi vertikal institusi, sebagaimana ditegaskan Merkel (2004), serta dijalankan dalam tata kelola kolaboratif antara negara dan masyarakat sipil (Ansell & Gash, 2008).
Roadmap pembangunan disiplin nasional dirancang dalam horizon panjang hingga 2060. Pada fase awal 2025–2030, fokus utama adalah pembentukan fondasi normatif dan kultural melalui harmonisasi regulasi, integrasi civic education, dan kampanye nasional yang membangun kesadaran kolektif. Pada fase 2030–2040, penekanan diarahkan pada institusionalisasi dengan penguatan digital governance, meritokrasi birokrasi, serta keterlibatan civil society organizations dalam pengawasan disiplin. Fase 2040–2050 ditandai dengan konsolidasi, di mana disiplin dijadikan pilar pembangunan dalam RPJPN 2045, diukur dengan Civic Discipline Index, dan diposisikan sebagai daya saing global. Fase terakhir, 2050–2060, merupakan puncak transformasi di mana disiplin telah melekat sebagai modal peradaban, menjadikan Indonesia model disiplin demokratis di Asia Tenggara dan memperkuat kepemimpinan global melalui soft power berbasis nilai (Nye, 2004).
Strategi penataan kebijakan disiplin nasional telah diuraikan melalui lima dimensi utama. Dimensi normatif menekankan harmonisasi regulasi agar selaras dengan prinsip demokrasi dan HAM, dimensi edukatif berfokus pada pendidikan kewargaan dan pembentukan karakter, dimensi institusional mengutamakan meritokrasi dan reformasi birokrasi, dimensi sosial-kultural menekankan pembentukan budaya disiplin kolektif, sedangkan dimensi teknologi memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui sistem monitoring digital. Kelima dimensi ini dipetakan dalam matriks kebijakan dengan aktor kunci, indikator, dan timeline yang jelas, sehingga memungkinkan implementasi yang konsisten lintas sektor.
Untuk memastikan efektivitas kebijakan, pengukuran kualitas disiplin nasional dilakukan dengan lima instrumen utama. Civic Discipline Index mengukur kesadaran publik dalam menjaga norma kolektif, Public Integrity Index menilai integritas birokrasi, Rule of Law Index mengevaluasi efektivitas penegakan hukum, Open Government Index menilai transparansi dan keterlibatan masyarakat, sedangkan Global Competitiveness Index mengaitkan disiplin dengan posisi Indonesia dalam persaingan global. Kombinasi indikator ini memungkinkan disiplin nasional dievaluasi secara obyektif dan komprehensif, sehingga menjadi basis untuk perbaikan kebijakan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, kesimpulan utama dari tulisan ini adalah bahwa disiplin nasional harus ditransformasikan dari sekadar instrumen kontrol menjadi civic virtue yang demokratis. Proses ini memerlukan strategi jangka panjang dengan tahapan yang terstruktur, integrasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat sipil. Apabila disiplin dapat ditanamkan sebagai nilai kolektif dan diukur secara konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, tetapi juga menempatkan diri sebagai negara demokratis yang stabil, berdaya saing, dan berpengaruh dalam tatanan global multipolar pada 2060.
Daftar Referensi
Acharya, A. (2014). The end of American world order. Polity Press.
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Aspinall, E., & Mietzner, M. (2010). Problems of democratisation in Indonesia: Elections, institutions and society. Institute of Southeast Asian Studies.
Bourdieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. Cambridge University Press.
Budiman, A. (1990). State and civil society in Indonesia. Monash Asia Institute.
Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector reform. Public Administration Review, 67(6), 1059–1066. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x
Diamond, L. (1999). Developing democracy: Toward consolidation. Johns Hopkins University Press.
Diamond, L., & Morlino, L. (2005). Assessing the quality of democracy. Johns Hopkins University Press.
Drechsler, W. (2018). Pathways to digital era public administration: The Estonian case. International Journal of Public Administration, 41(1), 25–42. https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1364393
Dwiyanto, A. (2011). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Etzioni, A. (1995). The spirit of community: Rights, responsibilities, and the communitarian agenda. Crown.
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29(2), 109–123. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4
Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. Pantheon Books.
Fukuyama, F. (2000). Social capital and civil society. International Monetary Fund Working Paper, WP/00/74.
Habermas, J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy. MIT Press.
Heryanto, A., & Hadiz, V. R. (2005). Post-authoritarian Indonesia: A comparative perspective. Critical Asian Studies, 37(2), 251–275. https://doi.org/10.1080/14672710500106371
Howlett, M., & Cashore, B. (2014). Conceptualizing public policy. In Engaging the public in policy-making (pp. 17–33). Routledge.
Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems. Oxford University Press.
Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence. Cambridge University Press.
Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. Information Systems Management, 29(4), 258–268. https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.
Lickona, T. (1991). Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility. Bantam.
Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, party, and religion: Explaining voting behavior in Indonesia. Comparative Political Studies, 40(7), 832–857. https://doi.org/10.1177/0010414006292113
Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance: A quasi-paradigm for government on the Web. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 371(1987), 20120382. https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382
Marradi, A. (1990). Classification, typology, taxonomy. Quality and Quantity, 24(2), 129–157. https://doi.org/10.1007/BF00209513
Merkel, W. (2004). Embedded and defective democracies. Democratization, 11(5), 33–58. https://doi.org/10.1080/13510340412331304598
Mietzner, M. (2012). Indonesia’s democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. Democratization, 19(2), 209–229. https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572620
North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.
Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs.
Parsons, T. (1951). The social system. Free Press.
Peters, B. G., & Pierre, J. (2012). The Sage handbook of public administration. SAGE Publications.
Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.
Schwab, K. (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum.
Setiawan, B. (2019). Pelanggaran lalu lintas dan budaya disiplin masyarakat Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 254–276. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.1961
Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index 2022. Transparency International.
Tyler, T. R. (2006). Why people obey the law. Princeton University Press.
United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations General Assembly.
World Justice Project. (2019). Rule of Law Index 2019. World Justice Project.
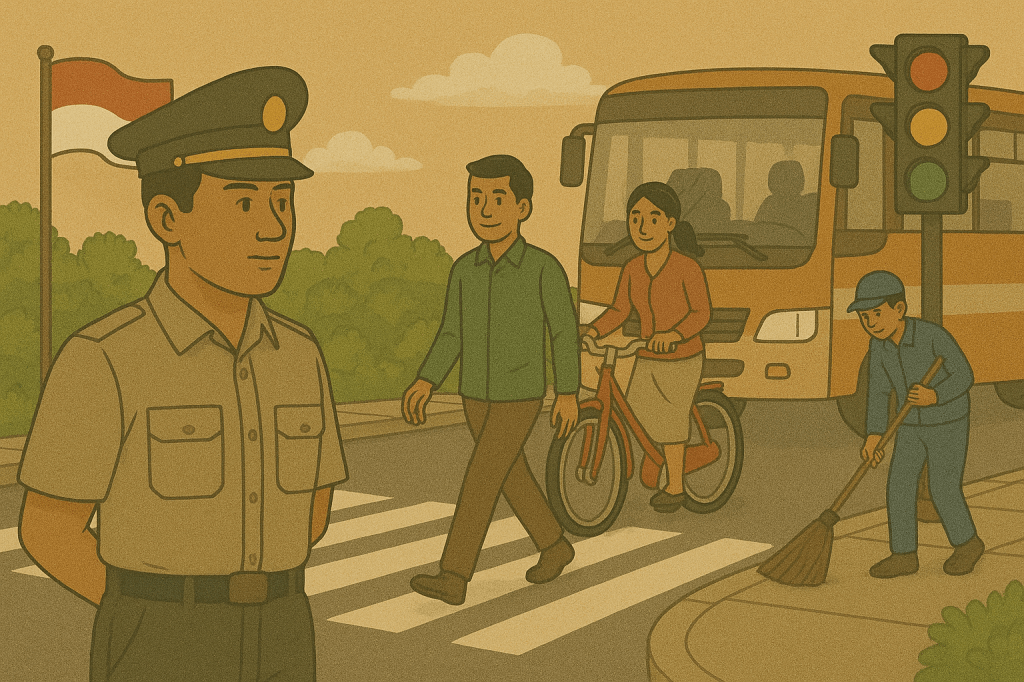
Leave a comment