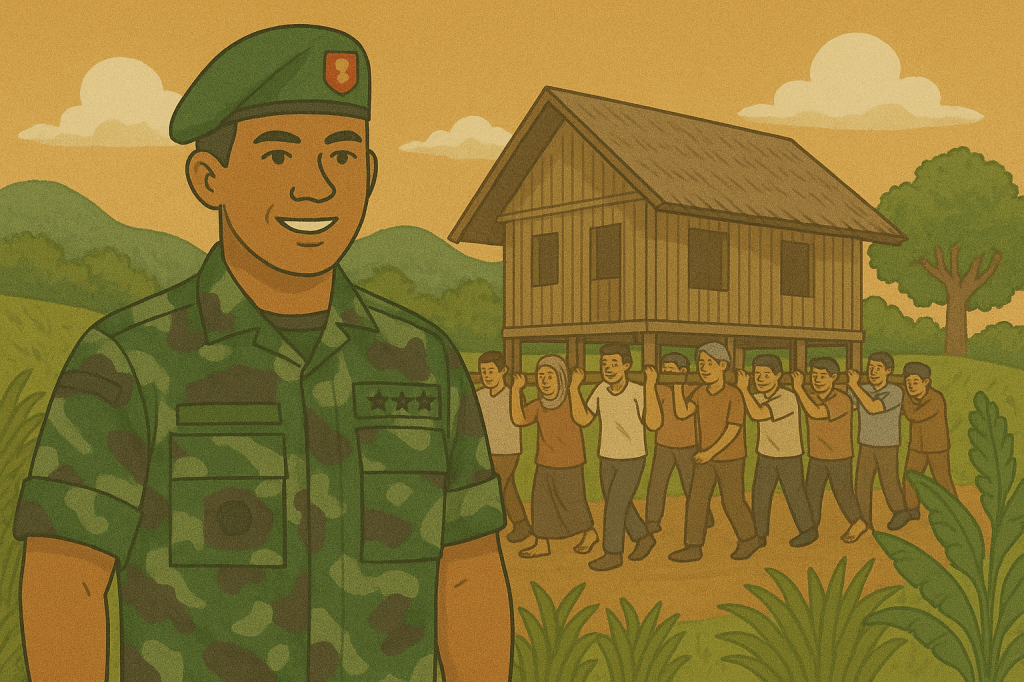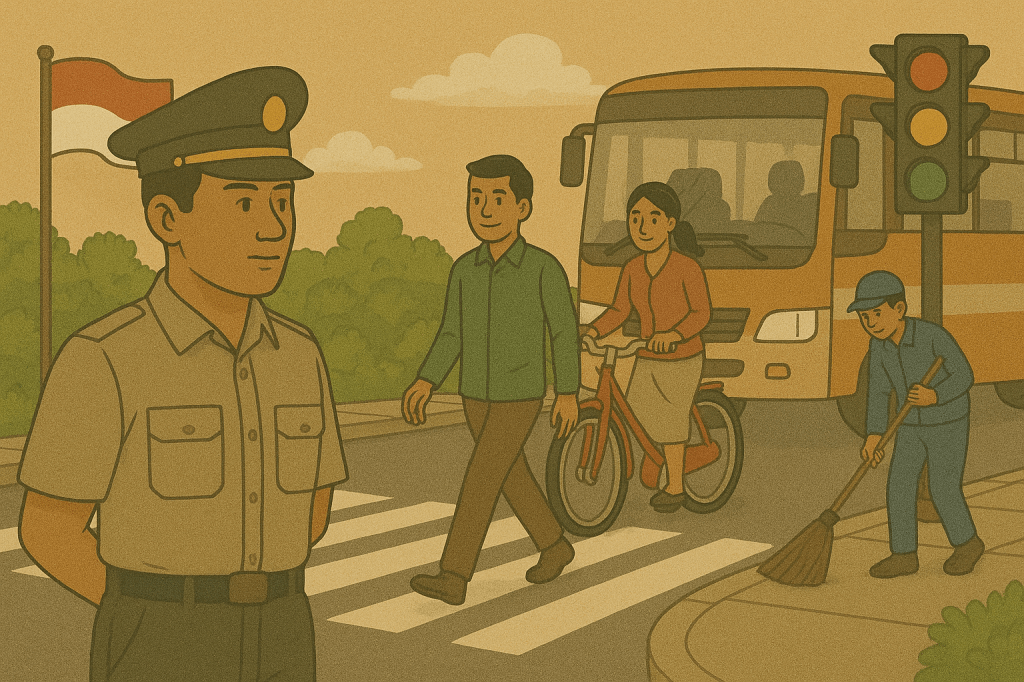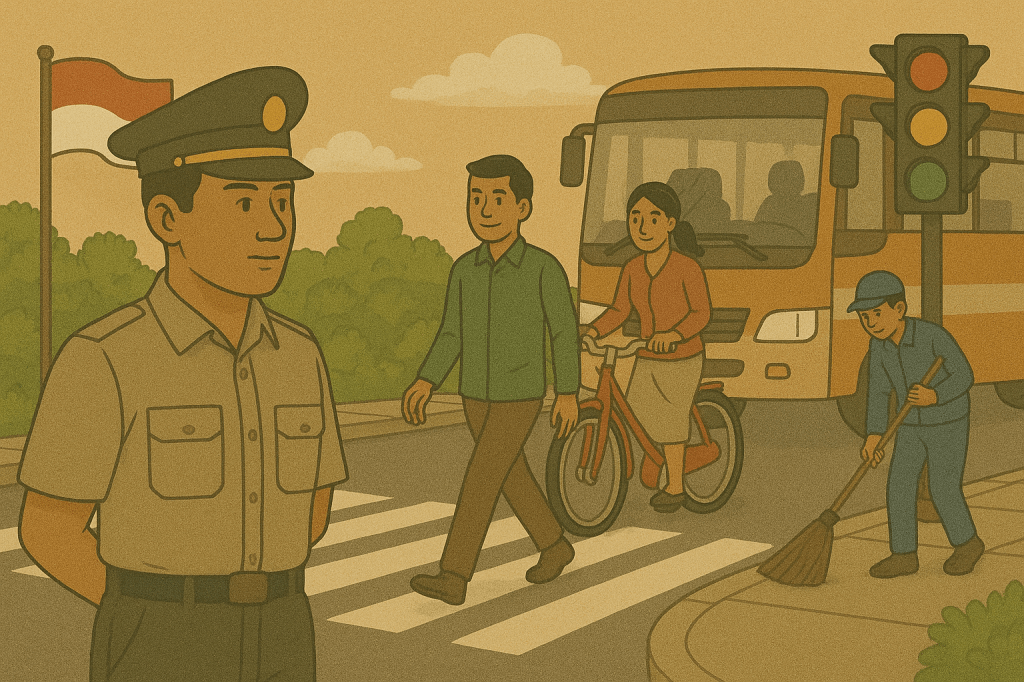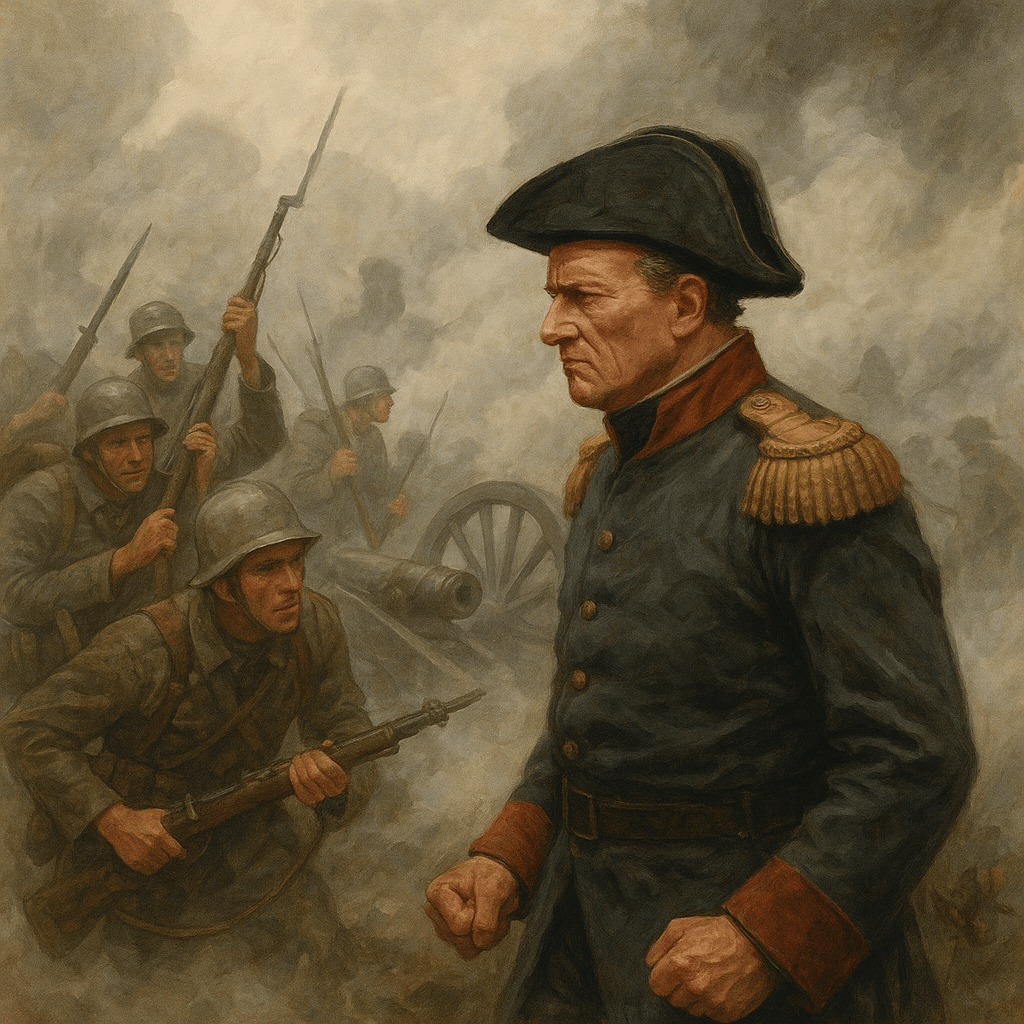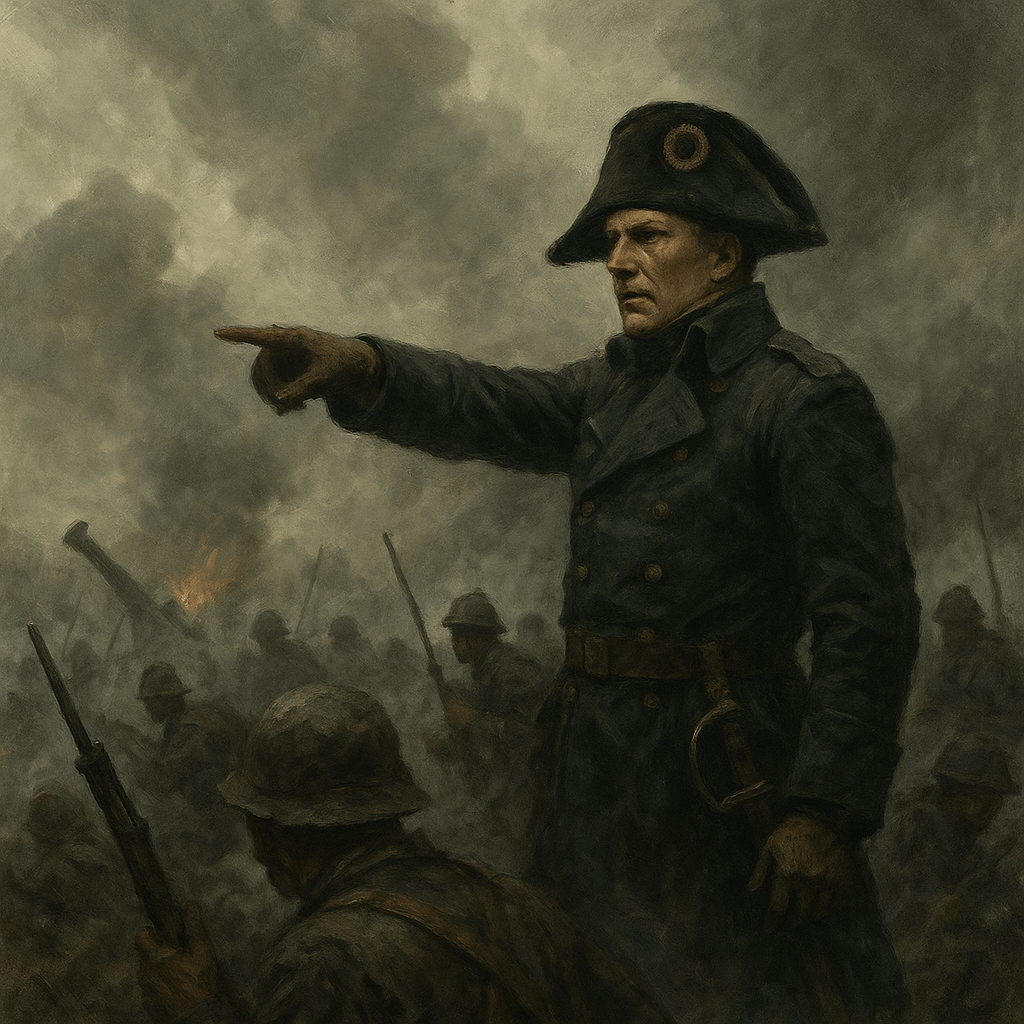Oleh: Bangkit Widodo
Dalam konteks pembangunan nasional dan transformasi industri strategis, PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA menempati posisi yang sangat vital dalam lanskap industrialisasi Indonesia. Didirikan pada tahun 1981 sebagai hasil restrukturisasi Balai Yasa Lokomotif Madiun milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT INKA menjadi BUMN manufaktur sarana perkeretaapian pertama yang berorientasi pada integrasi proses desain, produksi, dan pemeliharaan kereta api di Asia Tenggara (PT INKA, 2025a). Dengan demikian, kehadiran PT INKA tidak hanya merepresentasikan upaya kemandirian industri, tetapi juga manifestasi dari strategi negara dalam mengembangkan strategic manufacturing base berbasis teknologi menengah ke tinggi (medium–high technology industry) yang berdaya saing regional.
Secara konseptual, keberadaan PT INKA harus dilihat dalam kerangka state-led industrialization yang menekankan peran negara dalam menciptakan infant industry di sektor-sektor strategis yang memiliki spillover effect luas terhadap ekonomi nasional (Amsden, 1989; Chang, 2002). Sebagai industri yang padat modal, padat teknologi, dan berorientasi pada pasar domestik besar, sektor perkeretaapian menuntut kemampuan teknologi yang berkelanjutan, rantai pasok yang kuat, serta pasar domestik yang mampu menjamin economies of scale. Dalam hal ini, PT INKA tidak sekadar menjadi produsen sarana transportasi, tetapi juga simbol dari upaya negara untuk menginternalisasi kemampuan manufaktur, rekayasa, dan desain yang menjadi fondasi kemandirian industri pertahanan dan transportasi nasional (Hill, 2023).
Sejak awal berdirinya, PT INKA telah berperan penting dalam mendukung pengembangan sistem transportasi publik nasional, terutama dalam penyediaan armada kereta penumpang, diesel multiple unit (DMU), electric multiple unit (EMU), dan light rail transit (LRT). Produk-produk tersebut menjadi tulang punggung modernisasi armada PT KAI dan proyek strategis nasional seperti LRT Jabodebek dan LRT Sumatera Selatan, yang menggabungkan aspek teknologi transportasi perkotaan dengan efisiensi energi dan sustainable mobility (PT INKA, 2025b; Railway Gazette, 2019). Melalui partisipasi dalam proyek-proyek tersebut, PT INKA membangun learning curve industri yang tidak hanya meningkatkan kapabilitas manufaktur nasional, tetapi juga memperkuat absorptive capacity dalam adopsi dan adaptasi teknologi internasional (Cohen & Levinthal, 1990).
Lebih jauh lagi, ekspansi PT INKA ke pasar luar negeri seperti Bangladesh dan Filipina memperlihatkan transformasi dari industri domestik menjadi regional player di sektor transportasi berbasis rel. Kemampuan mengekspor DMU dan gerbong penumpang dengan spesifikasi tropis menunjukkan keunggulan adaptif dalam memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang yang memiliki kesamaan kondisi geografis dan sosial-ekonomi dengan Indonesia (ANTARA, 2020; Philippine News Agency, 2020). Ekspansi ini menjadi indikator bahwa proses industrial deepening yang dijalankan PT INKA telah menghasilkan keunggulan kompetitif berbasis pengalaman dan efisiensi biaya produksi.
Inisiatif pembangunan pabrik baru di Banyuwangi menandai fase industrialisasi lanjutan bagi PT INKA. Fasilitas baru ini dirancang dengan pendekatan export-oriented industrial cluster, yang bertujuan memperkuat daya saing ekspor sekaligus mengintegrasikan supply chain domestik dengan teknologi manufaktur modern (ANTARA, 2024; Indonesia Business Post, 2024). Dengan kapasitas produksi yang lebih besar dan fasilitas pengujian dinamis (dynamic test track), pabrik Banyuwangi diharapkan mampu mempercepat siklus inovasi dan sertifikasi produk sehingga dapat menembus pasar global dengan standar kualitas internasional.
Dengan demikian, urgensi strategis PT INKA tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai produsen sarana perkeretaapian, melainkan juga sebagai policy instrument negara dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan kemandirian teknologi nasional. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, PT INKA menjadi bagian integral dari upaya membangun ekosistem industri transportasi modern yang berkelanjutan, efisien, dan berdaya saing, yang pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya kedaulatan industri Indonesia di era globalisasi.
Kinerja dan Kapabilitas
Kinerja dan kapabilitas PT INKA sebagai produsen sarana perkeretaapian nasional mencerminkan perjalanan panjang proses pembelajaran industri yang berlangsung lebih dari empat dekade. Melalui kombinasi antara proyek-proyek domestik berskala besar dan penetrasi pasar ekspor ke berbagai negara berkembang, INKA telah berhasil menegaskan posisinya sebagai manufaktur kereta api terintegrasi pertama dan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Kinerja ini tidak hanya merefleksikan kemampuan produksi dan rekayasa teknis, tetapi juga menunjukkan bagaimana kebijakan industrialisasi yang dipimpin negara dapat menghasilkan technological upgrading yang berkelanjutan, sebuah capaian penting bagi ekonomi menengah seperti Indonesia.
Dalam konteks domestik, PT INKA memainkan peran sentral dalam modernisasi sistem transportasi publik berbasis rel. Salah satu tonggak pencapaian yang paling signifikan adalah keterlibatan perusahaan dalam pembangunan LRT Jabodebek, proyek urban rail pertama di Indonesia yang mengadopsi sistem Communications-Based Train Control (CBTC) dan beroperasi secara otomatis tanpa masinis. Implementasi sistem ini merupakan lompatan teknologi besar yang menandai peralihan dari sistem operasi manual ke era otomasi penuh dalam transportasi massal. Hal ini sekaligus memperlihatkan kemampuan INKA untuk berkolaborasi dalam proyek berteknologi tinggi yang melibatkan mitra global seperti Siemens dan Thales dalam bidang elektrifikasi, sinyal, dan sistem kendali. Melalui keterlibatan tersebut, INKA memperoleh absorptive capacity yang semakin matang, yakni kemampuan untuk mengidentifikasi, mengasimilasi, dan menerapkan pengetahuan eksternal guna memperkuat kemampuan rekayasa domestik (Cohen & Levinthal, 1990). Pengalaman ini memperluas kemampuan perusahaan dalam hal integrasi sistem, pengujian keselamatan, serta sertifikasi produk yang menjadi kunci bagi ekspansi ke pasar internasional.
Selain proyek LRT Jabodebek, PT INKA juga berperan penting dalam penyediaan armada electric multiple unit (EMU) dan diesel multiple unit (DMU) untuk layanan komuter dan antarkota yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Kolaborasi ini mendukung agenda pemerintah untuk memperluas akses transportasi publik yang efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Produk-produk EMU terbaru buatan INKA bahkan telah menjalani uji sertifikasi untuk rute Jabodetabek pada tahun 2025, menandai peningkatan kualitas produksi yang mendekati standar global (RollingstockWorld, 2025). Dalam perspektif ekonomi industri, keberhasilan INKA di pasar domestik tidak hanya merefleksikan keberhasilan komersial, tetapi juga mengindikasikan terbentuknya technological base nasional yang memungkinkan Indonesia beranjak dari fase industri perakitan menuju industri dengan kemampuan desain dan integrasi sistem (Hobday, 1995; Matthews & Maharani, 2022). Penguasaan kompetensi dalam bidang desain adaptif, testing and commissioning, serta layanan purna jual memperkuat posisi INKA dalam rantai nilai industri perkeretaapian modern.
Sementara itu, di ranah internasional, capaian ekspor PT INKA menandai babak baru dalam proses industrial upgrading Indonesia. Sejak 2019, INKA berhasil menembus pasar ekspor dengan mengirimkan diesel multiple unit (DMU) dan gerbong penumpang ke Bangladesh serta Filipina. Kontrak dengan Bangladesh Railway, yang melibatkan pengiriman lebih dari 250 gerbong dengan spesifikasi meter gauge, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan kustomisasi produk sesuai standar internasional dan kondisi geografis tropis (Railway Gazette, 2019). Sementara itu, ekspor ke Philippine National Railways (PNR) pada 2019–2020 mempertegas reputasi Indonesia sebagai negara yang mampu memproduksi rolling stock berstandar tinggi untuk pasar Asia Tenggara (ANTARA, 2020; Philippine News Agency, 2020). Selain nilai ekonominya yang signifikan, ekspor tersebut juga memiliki makna strategis dalam konteks South–South cooperation, di mana Indonesia memainkan peran sebagai pemasok teknologi dan mitra industri bagi negara-negara berkembang lain di kawasan (Sukma, 2021).
Dari perspektif pasar global, keberhasilan ekspor ini menunjukkan adanya product-market fit yang kuat antara produk INKA dan kebutuhan negara-negara berkembang yang masih menggunakan rel berukuran metric dan meter gauge. Kombinasi antara harga yang kompetitif, kapasitas penumpang yang besar, serta desain yang tahan terhadap iklim tropis menjadikan produk INKA sangat relevan bagi segmen pasar menengah yang belum sepenuhnya dilayani oleh produsen besar dari Jepang atau Eropa. Posisi strategis ini membuka peluang bagi INKA untuk menjadi niche exporter di bidang solusi transportasi rel yang terjangkau dan adaptif, terutama di Asia Selatan, Afrika Timur, dan Pasifik (Matthews, 2025). Selain itu, setiap proyek ekspor berfungsi sebagai wahana pembelajaran kelembagaan. Melalui keterlibatan dalam tender internasional, INKA memperoleh pengalaman dalam pemenuhan standar mutu, manajemen kontrak global, serta pembiayaan berbasis export credit agency (ECA). Kemampuan ini memperkuat kredibilitas korporasi di mata lembaga pembiayaan internasional dan memperluas kapasitas kelembagaan perusahaan untuk mengelola proyek dengan kompleksitas tinggi.
Capaian di tingkat domestik dan internasional ini menunjukkan bahwa INKA telah mengembangkan dual capability yang sangat penting bagi kelangsungan industrinya. Di satu sisi, INKA menguasai kemampuan adaptasi teknis yang memungkinkan perusahaan memenuhi kebutuhan pasar domestik dengan karakteristik geografis dan sosial yang unik. Di sisi lain, INKA juga mengembangkan kemampuan kustomisasi dan sertifikasi yang diperlukan untuk bersaing di pasar global. Kombinasi kedua kemampuan ini memperkuat daya tahan perusahaan terhadap fluktuasi permintaan dan memperluas industrial resilience nasional (Bitzinger, 2016). Dengan demikian, INKA bukan lagi sekadar assembler domestik, tetapi telah bertransformasi menjadi adaptive manufacturer yang menggabungkan keunggulan efisiensi produksi dengan kemampuan integrasi sistem dan ekspor berorientasi teknologi.
Kinerja INKA dalam satu dekade terakhir dengan demikian dapat dibaca sebagai cermin keberhasilan industrialisasi Indonesia di sektor strategis. Ia memperlihatkan bahwa dengan kebijakan industri yang konsisten, kemitraan global yang selektif, dan komitmen terhadap pembelajaran teknologi berkelanjutan, perusahaan milik negara dapat menjadi katalis bagi transformasi struktural ekonomi nasional. INKA, dalam konteks ini, bukan hanya produsen sarana transportasi, tetapi simbol kemandirian teknologi Indonesia yang sedang menuju fase industrialisasi matang dan berdaya saing global.
Permintaan Domestik: Jendela Peluang 2025–2029
Peningkatan permintaan domestik terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian nasional pada periode 2025–2029 menciptakan momentum penting bagi revitalisasi industri kereta api Indonesia, khususnya bagi PT INKA sebagai produsen utama rolling stock. Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menempatkan sektor transportasi sebagai katalis integrasi ekonomi antarwilayah. Pemerintah menargetkan peningkatan konektivitas melalui perluasan jaringan rel yang lebih merata antara Jawa dan luar Jawa, sebagai upaya mengoreksi ketimpangan pembangunan infrastruktur dan memperkuat struktur ekonomi nasional berbasis kewilayahan (KPMG, 2025; Bappenas, 2024).
Dari perspektif spasial, prioritas pembangunan jaringan kereta api mencakup sejumlah proyek strategis. Di Sulawesi, proyek Trans-Sulawesi Railway ditargetkan meningkat dari sekitar 71 kilometer menjadi lebih dari 700 kilometer sepanjang dekade ini. Pengembangan jalur ini merupakan bagian dari agenda besar membangun koridor logistik timur Indonesia yang lebih efisien dan terhubung dengan pelabuhan utama di Makassar, Parepare, dan Manado. Di Kalimantan, rencana pembangunan jaringan baru sepanjang 1.200 kilometer diarahkan untuk mendukung pengangkutan batubara, hasil perkebunan, serta mobilitas pekerja dan barang menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara itu, di Sumatra, akselerasi jaringan dari 1.854 kilometer menjadi hampir 2.900 kilometer bertujuan memperkuat konektivitas antarprovinsi dan menurunkan biaya logistik antardaerah. Di Papua, proyek jalur Jayapura–Sarmi dan Manokwari–Bintuni menjadi langkah awal pengembangan sistem transportasi terpadu di kawasan dengan tingkat keterisolasian tertinggi di Indonesia (Indonesia Business Post, 2025).
Selain perluasan jaringan, pembangunan ibu kota baru Nusantara (IKN) menghadirkan peluang yang signifikan sebagai pilot area bagi pengujian dan penerapan teknologi perkeretaapian modern. Sistem autonomous rail transit (ART) yang telah menjalani uji operasi pada 17 Agustus 2024 menjadi simbol transisi Indonesia menuju smart mobility ecosystem berbasis otomasi dan energi bersih (PwC Indonesia, 2024). Sistem ART di IKN tidak hanya berfungsi sebagai moda transportasi perkotaan, tetapi juga sebagai laboratorium inovasi untuk pengujian teknologi driverless, integrasi sensor cerdas, dan efisiensi energi menggunakan battery-electric propulsion system. Dalam konteks kebijakan industri nasional, proyek IKN dapat dimanfaatkan sebagai living lab bagi PT INKA untuk mengembangkan lini produk baru yang menggabungkan otomasi, keberlanjutan, dan kemandirian teknologi.
Pada skala metropolitan, permintaan terhadap fleet renewal dan modernisasi layanan komuter semakin meningkat, terutama di wilayah Jabodetabek. Uji sertifikasi terhadap rangkaian EMU generasi terbaru buatan PT INKA yang bekerja sama dengan CRRC pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Indonesia mulai beralih dari ketergantungan impor menuju technology co-production yang lebih seimbang (RollingstockWorld, 2025). Proyek ini menandakan peningkatan kapasitas nasional dalam memproduksi rangkaian komuter dengan standar keselamatan, efisiensi energi, dan kenyamanan yang mendekati benchmark global. Dengan jumlah penumpang KRL Jabodetabek yang mencapai lebih dari satu juta orang per hari, kebutuhan akan armada baru menjadi salah satu demand driver terbesar bagi industri domestik.
Jika dikombinasikan dengan pengembangan MRT Jakarta Fase 3, perluasan LRT Jakarta dan Jabodebek, serta rencana pembangunan kereta perkotaan di Surabaya, Medan, dan Bandung, maka terbentuklah demand pipeline yang sangat besar bagi industri manufaktur kereta nasional. PT INKA, dalam konteks ini, memiliki posisi strategis untuk menjadi prime contractor dalam penyediaan sarana, baik untuk proyek pemerintah pusat maupun kerja sama daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi yang bersifat integratif tidak hanya berdampak pada mobilitas publik, tetapi juga menjadi instrumen industrial deepening yang memperluas learning-by-doing capacity industri nasional.
Kenaikan permintaan domestik ini secara makroekonomis juga terkait erat dengan proses urbanisasi dan pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang diproyeksikan meningkat signifikan pada dekade 2020-an. Meningkatnya kebutuhan mobilitas perkotaan mendorong pergeseran dari penggunaan kendaraan pribadi menuju moda transportasi publik berbasis rel yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berbiaya lebih rendah per kapita. Menurut teori induced demand dalam ekonomi transportasi (Goodwin, 1996), peningkatan kapasitas dan kenyamanan sistem transportasi publik akan menciptakan peningkatan permintaan secara endogen, yang pada gilirannya memperluas pasar potensial bagi produsen seperti INKA. Dengan demikian, policy-induced demand yang dihasilkan oleh proyek pemerintah menjadi engine of growth bagi sektor manufaktur domestik.
Di sisi lain, meningkatnya permintaan domestik juga mendorong kebutuhan akan reformasi kebijakan pengadaan yang lebih fleksibel dan adaptif. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan salah satu instrumen strategis yang dirancang untuk memperkuat basis industri nasional melalui peningkatan kandungan lokal dalam setiap proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung pada keseimbangan antara ambisi industrialisasi dan realitas kapasitas industri dalam negeri. Pada tahun 2023, rencana KAI Commuter (KCI) untuk membeli rangkaian bekas dari Jepang tertunda karena tidak memenuhi ambang batas TKDN sebesar 40%, yang mensyaratkan tingkat kandungan lokal minimal untuk setiap kontrak yang didanai oleh anggaran pemerintah (Jakarta Post, 2023). Kasus tersebut menjadi pelajaran penting mengenai perlunya policy agility dalam penerapan regulasi industri strategis.
Pemerintah kemudian melakukan reformasi regulasi pada periode 2024–2025 dengan menyesuaikan kebijakan TKDN agar lebih kontekstual terhadap dinamika industri (Hogan Lovells, 2024; ARMA Law, 2025). Pelonggaran dan penyelarasan aturan di sektor terkait, terutama kelistrikan dan transportasi, memberikan fleksibilitas bagi proyek-proyek yang belum dapat memenuhi ambang batas kandungan lokal karena keterbatasan pasokan domestik. Pendekatan baru ini memungkinkan adanya mekanisme fallback sementara, di mana proyek tetap dapat berjalan sembari disertai dengan rencana peningkatan kandungan lokal secara bertahap. Dengan demikian, semangat substitusi impor tetap terjaga, tetapi tanpa menghambat kelangsungan pembangunan infrastruktur strategis (ANTARA, 2025).
Bagi PT INKA, reformasi kebijakan TKDN membuka peluang besar untuk memperluas kolaborasi teknologi melalui skema co-production dan technology sharing dengan mitra global, khususnya dalam pengembangan platform EMU dan subsystem engineering. Fleksibilitas ini memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar dan teknologi sekaligus menjaga local value-added yang menjadi basis legitimasi industri nasional. Selain itu, kebijakan yang lebih adaptif juga mengurangi risiko supply crunch dalam program fleet renewal, yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam siklus pengadaan armada kereta api.
Dengan demikian, kombinasi antara pertumbuhan permintaan domestik, pembaruan kebijakan industri, dan transformasi struktural dalam pengadaan negara membentuk ekosistem yang kondusif bagi kebangkitan industri perkeretaapian nasional. PT INKA, yang berada di titik persilangan antara kepentingan pembangunan dan inovasi teknologi, berpeluang besar memanfaatkan jendela strategis 2025–2029 sebagai momentum akselerasi menuju regional competitiveness dan kemandirian industri transportasi berbasis rel di Indonesia.
Kapasitas Industri: Skala, Teknologi, dan Ekspansi Banyuwangi
Pembangunan pabrik baru PT INKA di Banyuwangi menandai tonggak penting dalam evolusi kapasitas industri manufaktur kereta api nasional. Dengan luas mencapai 83 hektare dan investasi sekitar Rp1,6 triliun, fasilitas ini dirancang untuk menggandakan kapasitas produksi sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain regional dalam industri rolling stock (Rail Journal, 2019; The Jakarta Post, 2019). Ekspansi Banyuwangi bukan sekadar perluasan fisik dari basis manufaktur Madiun, tetapi merupakan langkah strategis menuju model export-oriented manufacturing hub yang terintegrasi dengan rantai pasok domestik dan global. Dengan target full operation pada tahun 2025, pabrik ini dilengkapi dengan dynamic test track sepanjang ±3 km serta sistem uji kualitas berstandar internasional, dua infrastruktur penting yang menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi standar sertifikasi global serta mempercepat time-to-market (ANTARA, 2024; Indonesia Business Post, 2024).
Secara konseptual, pembangunan pabrik Banyuwangi dapat dibaca melalui kerangka industrial upgrading dan technological deepening. Dalam literatur pembangunan industri, fase ekspansi semacam ini menunjukkan transisi dari manufaktur berbasis perakitan (assembly-based industry) menuju industri rekayasa terintegrasi (integrated engineering industry), di mana kemampuan desain, sertifikasi, dan integrasi sistem menjadi penentu daya saing (Amsden, 1989; Matthews & Maharani, 2022). Keberadaan dua klaster utama, Madiun sebagai basis produksi domestik dan Banyuwangi sebagai pusat ekspor, membentuk industrial footprint yang memungkinkan PT INKA menyeimbangkan kebutuhan batching production untuk pasar dalam negeri dan pengembangan customized manufacturing untuk permintaan luar negeri.
Secara operasional, pabrik Banyuwangi dirancang untuk meningkatkan efisiensi rantai produksi melalui batch-based manufacturing system yang memungkinkan produksi massal EMU, DMU, dan LRT dengan waktu produksi yang lebih pendek. Implementasi sistem ini mengoptimalkan alur kerja dari desain hingga commissioning, sehingga mempercepat pengiriman produk dan menurunkan biaya logistik. Di sisi lain, fasilitas baru ini juga difungsikan sebagai pusat module localization, yakni proses peningkatan kandungan lokal untuk komponen bernilai tinggi seperti bogie, sistem traksi, sistem pengereman, dan HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning). Penguatan pada level modular ini sangat krusial karena menentukan seberapa jauh Indonesia mampu melakukan technological localization terhadap subsistem kunci yang selama ini masih bergantung pada pemasok asing.
Selain sebagai basis produksi, Banyuwangi juga diproyeksikan menjadi pusat layanan maintenance, repair, and overhaul (MRO) untuk armada domestik dan regional. Dalam konteks industri perkeretaapian global, MRO merupakan segmen bernilai tinggi yang mampu menghasilkan pendapatan berulang (recurring revenue) serta memperpanjang siklus hidup produk (life-cycle value). Keberadaan fasilitas MRO yang memadai memungkinkan INKA menawarkan kontrak jangka panjang berbasis availability kepada operator kereta di dalam dan luar negeri, sehingga memperkuat posisi korporasi dalam rantai nilai pascaproduksi (after-sales ecosystem). Strategi ini juga sejalan dengan kecenderungan global di mana produsen rolling stock bergeser dari penjualan aset tunggal menuju model bisnis berbasis layanan (product-as-a-service).
Lebih jauh, pabrik Banyuwangi memiliki nilai strategis sebagai pusat technological convergence. Fasilitas ini dirancang agar mampu mengakomodasi pengembangan teknologi baru seperti sistem driverless (CBTC/GoA4), hybrid propulsion, serta penggunaan material ringan (lightweight composites). Dengan demikian, Banyuwangi tidak hanya memperluas kapasitas produksi, tetapi juga menjadi testing ground bagi integrasi teknologi masa depan, termasuk kendaraan rel listrik bertenaga baterai dan sistem smart diagnostics. Dalam jangka menengah, hal ini akan memperkuat design authority domestik serta mengurangi ketergantungan pada lisensi teknologi asing.
Di sisi kelembagaan, ekspansi Banyuwangi juga mencerminkan penerapan prinsip industrial decentralization, yang berpotensi menumbuhkan ekosistem industri baru di wilayah timur Jawa. Kehadiran klaster manufaktur besar di Banyuwangi akan mendorong regional industrial linkage dengan sektor logistik, pelabuhan, pendidikan vokasi, serta UKM komponen lokal. Dengan demikian, dampak ekonomi yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada peningkatan kapasitas produksi INKA, tetapi juga menciptakan industrial spillover yang memperkuat basis manufaktur daerah. Fenomena ini sejalan dengan teori new economic geography yang menekankan pentingnya pembentukan aglomerasi industri untuk mendorong inovasi dan efisiensi (Krugman, 1991).
Pabrik Banyuwangi pada akhirnya diharapkan menjadi simbol dari second wave of industrialization di sektor transportasi Indonesia, yakni industrialisasi yang berorientasi pada nilai tambah, kemandirian teknologi, dan daya saing ekspor. Apabila dirancang dan dijalankan dengan tata kelola yang baik, ekspansi ini dapat memperkuat posisi INKA sebagai regional rolling stock manufacturer yang mampu bersaing di pasar Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika. Kombinasi antara engineering capability, production scale, dan technological localization menjadikan Banyuwangi bukan sekadar fasilitas baru, melainkan infrastruktur strategis bagi keberlanjutan industri perkeretaapian nasional di era kompetisi global.
Tantangan Struktural Sektor
Meskipun prospek pertumbuhan industri perkeretaapian nasional cukup besar, sejumlah tantangan struktural masih membayangi keberlanjutan dan daya saing sektor ini. Tantangan pertama berkaitan dengan risiko pembiayaan mega-proyek. Pengalaman proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC Whoosh) menunjukkan bahwa cost overrun, beban utang, serta proyeksi permintaan yang meleset dapat menimbulkan tekanan terhadap stabilitas keuangan BUMN perkeretaapian (The Australian, 2025). Implikasinya bagi INKA adalah perlunya pendekatan yang lebih disiplin dalam perencanaan proyek, khususnya melalui penerapan skema Public–Private Partnership (PPP), availability payment, dan viability gap funding yang mampu membagi risiko antara pemerintah, operator, dan produsen. Disiplin permintaan, terutama dalam hal kalibrasi proyeksi jumlah penumpang (ridership) dan integrasi antarmoda, juga menjadi kunci agar portofolio pesanan (order book) tidak terjebak pada fluktuasi fiskal jangka pendek.
Tantangan kedua menyangkut kepastian kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penguatan rantai pasok. TKDN yang diterapkan terlalu kaku dapat memperlambat proses pengadaan ketika kapasitas domestik belum memadai, sedangkan kebijakan yang terlalu longgar tanpa peta jalan industrialisasi justru berpotensi melemahkan learning curve industri. Oleh karena itu, keseimbangan antara localization dan global sourcing harus dikelola secara strategis melalui kebijakan industri berbasis technology roadmap per subsistem, seperti traksi, sistem sinyal (signalling), komunikasi, dan material ringan. Pendekatan ini memastikan proses lokalisasi berjalan bertahap, tetapi tetap searah dengan agenda peningkatan kemampuan teknologi nasional.
Tantangan berikutnya terletak pada aspek standardisasi dan sertifikasi. Transisi menuju sistem driverless, teknologi low-emission, dan penerapan regenerative braking menuntut standar keselamatan, kompatibilitas elektromagnetik (EMC), serta keamanan siber yang sebanding dengan standar internasional. Keterbatasan fasilitas uji domestik dapat menjadi hambatan utama dalam percepatan sertifikasi produk baru. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas pengujian dan sertifikasi terintegrasi menjadi prioritas untuk mempercepat time-to-market sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk buatan Indonesia.
Selain itu, penguatan sumber daya manusia dan kemampuan desain menjadi tantangan fundamental. PT INKA perlu memperluas kapasitas dalam bidang systems engineering, analisis Reliability, Availability, Maintainability, and Safety (RAMS), serta Life Cycle Costing (LCC). Implementasi pendekatan digital seperti Product Lifecycle Management (PLM) dan Model-Based Systems Engineering (MBSE) diperlukan untuk mempercepat inovasi, mengurangi kesalahan desain, dan meningkatkan koordinasi antarproyek. Transformasi dari model build-to-print menuju design-authority parsial atau penuh pada produk strategis merupakan langkah penting untuk menegaskan kemandirian teknologi nasional.
Tantangan terakhir adalah integrasi antara proyek infrastruktur dan operasi layanan. Ketidakseimbangan antara pembangunan jaringan dan kesiapan operasional, seperti yang terlihat pada beberapa proyek urban rail yang belum sepenuhnya terintegrasi, dapat mengurangi tingkat keterisian penumpang (ridership utilization) dan memengaruhi bankability proyek. Tanpa through-running, headway yang konsisten, dan integrasi tarif antarmoda, utilisasi armada akan rendah, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas permintaan bagi produsen seperti INKA. Oleh karena itu, keberhasilan industrialisasi perkeretaapian bergantung pada sinkronisasi yang kuat antara desain proyek, pola operasi, kebijakan tarif, dan pengembangan kawasan berbasis transit-oriented development (TOD).
Dalam keseluruhan konteks ini, ekspansi Banyuwangi hanya akan mencapai potensi optimalnya apabila diiringi oleh pembenahan sistemik terhadap tantangan struktural tersebut. Reformasi kebijakan, penguatan kapasitas teknologi, dan koordinasi lintas-sektor merupakan prasyarat bagi PT INKA untuk bergerak dari sekadar national champion menuju regional system integrator yang berdaya saing global.
Prospek: Dari National Champion ke Regional Player
Transformasi PT INKA dari sekadar national champion menjadi regional player di industri perkeretaapian menuntut kombinasi antara kapasitas produksi, inovasi teknologi, dan penetrasi pasar lintas negara. Dalam konteks ekonomi industri, posisi national champion mengacu pada perusahaan milik negara yang didorong untuk menjadi ujung tombak industrialisasi nasional sekaligus instrumen diplomasi ekonomi (Amsden, 1989; Chang, 2002). Namun, untuk bertransisi ke tingkat regional player, diperlukan kemampuan bersaing dalam tiga aspek utama: keunggulan biaya dan skala produksi (cost and scale efficiency), adaptasi terhadap standar teknologi internasional, serta kapasitas kelembagaan untuk membangun jejaring pasar dan pembiayaan lintas batas. Dalam horizon 2025–2029, berbagai proyek strategis domestik dan global membuka peluang konkret bagi INKA untuk melangkah ke arah tersebut.
Di sektor urban rail dan fleet renewal, pertumbuhan jaringan transportasi perkotaan seperti MRT, LRT, dan sistem komuter Jabodetabek menghadirkan home market yang memadai untuk mencapai economies of scale. Ekspansi proyek-proyek seperti MRT Jakarta Fase 3, perluasan LRT Jabodebek dan Jakarta, serta rehabilitasi armada KRL Jabodetabek memperluas ruang produksi bagi INKA. Keikutsertaan perusahaan dalam uji sertifikasi EMU generasi baru pada 2025 menandai kematangan teknologi dalam produksi rangkaian listrik modern yang efisien, ergonomis, dan berstandar keselamatan internasional (RollingstockWorld, 2025; PT INKA, 2025c). Kapasitas domestik yang besar ini memungkinkan INKA mengembangkan product platform modular untuk segmen komuter dan antarkota non-HSR (non–high-speed rail). Model modular memberi fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan konfigurasi armada, baik untuk kapasitas, sistem traksi, maupun desain interior, tanpa menambah biaya desain baru setiap kali terjadi variasi permintaan. Selain itu, peluang refurbishment terhadap armada lama milik KAI dan operator daerah dapat menjadi pasar tambahan yang stabil, sekaligus memperluas after-sales ecosystem dalam negeri.
Ekspansi jaringan perkeretaapian di luar Jawa juga menjadi penentu masa depan industri. Program pembangunan jalur di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua yang menjadi prioritas RPJMN 2025–2029 membuka segmen pasar baru untuk kereta non-elektrifikasi seperti DMU dan EMU battery-hybrid yang sesuai dengan karakteristik greenfield track dan topografi menantang (KPMG, 2025; Indonesia Business Post, 2025). Permintaan terhadap produk ini menuntut inovasi pada desain bogie yang lebih lentur (track-friendly), konsumsi energi rendah, serta kemampuan beroperasi pada jalur dengan infrastruktur terbatas. Dalam perspektif industri strategis, pasar ini sangat penting karena memungkinkan Indonesia membangun basis permintaan berkelanjutan di wilayah timur yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem transportasi berbasis rel. Dengan demikian, INKA berpotensi menjadi penyedia solusi end-to-end bagi pembangunan jaringan baru di luar Jawa, mulai dari sarana, desain lintasan, hingga sistem pemeliharaan.
Peluang berikutnya datang dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berfungsi sebagai living laboratory untuk sistem transportasi cerdas. Implementasi autonomous rail transit (ART) di IKN yang telah diuji sejak 2024 memperlihatkan arah baru dalam integrasi otomasi, efisiensi energi, dan keberlanjutan (PwC Indonesia, 2024). Dalam konteks ini, IKN menjadi sandbox environment bagi pengujian teknologi Automatic Train Operation (ATO), sistem smart operations, dan integrasi energi terbarukan. Apabila INKA mampu berperan aktif dalam desain, integrasi, dan sertifikasi sistem ini, pengalaman tersebut akan menjadi exportable portfolio untuk proyek perkotaan di negara-negara Asia dan Afrika yang sedang membangun sistem transportasi cerdas menengah (medium-capacity smart rail systems). Keberhasilan di IKN akan memperkuat posisi INKA sebagai produsen yang tidak hanya kompetitif secara harga, tetapi juga berkemampuan teknologi maju.
Dari sisi internasional, momentum rebound ekspor memberikan peluang yang signifikan. Reputasi PT INKA di pasar Bangladesh dan Filipina telah membentuk credibility pathway yang dapat diperluas ke negara-negara Afrika dan Asia Selatan (ANTARA, 2020; Philippine News Agency, 2020; Railway Gazette, 2019). Pasar-pasar tersebut memiliki kesamaan karakteristik—yakni spesifikasi rel meter gauge, kebutuhan akan solusi transportasi hemat biaya, serta iklim tropis yang mirip dengan Indonesia. INKA dapat memperkuat daya saingnya dengan menawarkan paket terintegrasi yang tidak hanya mencakup pasokan rolling stock, tetapi juga skema pembiayaan berbasis export credit agency (ECA), supplier’s credit, dan kemitraan MRO lokal. Model ini terbukti efektif digunakan oleh perusahaan manufaktur kereta global seperti Alstom dan Hyundai Rotem dalam menembus pasar negara berkembang. Jika dirancang dengan baik, pendekatan ini akan menciptakan value chain internationalization yang memperluas keberlanjutan bisnis ekspor INKA.
Sementara itu, ekspansi Banyuwangi akan berperan sebagai fondasi bagi transformasi PT INKA menjadi export-grade manufacturer. Fasilitas uji dinamis sepanjang 3 km dan sertifikasi mutu berstandar internasional memungkinkan percepatan product qualification dan sertifikasi lintas negara (ANTARA, 2024; Indonesia Business Post, 2024). Dengan pengelolaan kapasitas produksi yang terintegrasi antara Madiun dan Banyuwangi, INKA dapat menjalankan strategi parallel production di mana proyek domestik dan ekspor dikerjakan secara simultan tanpa mengorbankan efisiensi. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan order book dan memastikan keberlanjutan arus kas, terutama dalam menghadapi siklus fiskal proyek pemerintah.
Dalam perspektif jangka menengah, kombinasi antara kapasitas industri Banyuwangi, inovasi teknologi di IKN, dan ekspansi pasar di luar Jawa akan memperkuat posisi INKA dalam rantai nilai global. Perusahaan dapat bertransisi dari original equipment manufacturer (OEM) menjadi system integrator regional yang mampu mengoordinasikan jaringan pemasok dan mitra teknologi lintas negara. Transformasi ini juga membuka ruang bagi industrial diplomacy, di mana keberhasilan ekspor dan kolaborasi teknologi menjadi instrumen politik luar negeri Indonesia di bidang ekonomi dan pertahanan. Dengan demikian, prospek INKA tidak hanya ditentukan oleh dinamika pasar domestik, tetapi juga oleh kemampuannya memanfaatkan peluang geopolitik dan regional untuk memperluas jejaring industri dan inovasi.
Strategi Akselerasi: Rekomendasi Kebijakan dan Korporasi
Prospek besar tersebut hanya dapat terwujud jika diikuti oleh strategi akselerasi yang konsisten, baik di tingkat pemerintah maupun korporasi. Di sisi pemerintah, koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar kebijakan industri, fiskal, dan transportasi saling memperkuat. Pemerintah perlu menyempurnakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan availability payment bertahap, dukungan selektif dari pemerintah (sovereign support), serta alokasi risiko yang layak secara finansial. Skema pembiayaan inovatif seperti rail funding facility yang mengaitkan belanja armada dengan kinerja layanan (service-linked finance) perlu dikembangkan agar operator dan pabrikan memiliki kepastian pendapatan jangka panjang. Selain itu, pemerintah harus menetapkan technology roadmap per subsistem, mulai dari traksi, bogie, sistem pengereman, HVAC, hingga TCMS/CBTC, dengan target TKDN bertahap (misalnya 30–50%) serta offset berbasis penelitian bersama untuk memastikan kesinambungan technological upgrading.
Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan railway test center nasional sebagai fasilitas sertifikasi independen yang mampu menguji sistem otomasi, keamanan siber, dan adaptasi iklim tropis. Tanpa fasilitas ini, waktu sertifikasi akan tetap menjadi bottleneck dalam ekspansi produk baru. Selain itu, pengelolaan demand management melalui tarif terpadu, integrasi antarmoda, dan pengembangan kawasan berbasis transit-oriented development (TOD) perlu diperkuat untuk menjamin ridership yang tinggi dan arus kas operator yang stabil. Hal ini akan menciptakan siklus berkelanjutan di mana peningkatan permintaan transportasi publik memperkuat stabilitas industri perkeretaapian domestik. Di atas segalanya, konsistensi kebijakan TKDN pascarelaksasi menjadi prasyarat penting. Fleksibilitas pada fase transisi diperlukan, tetapi harus disertai kerangka waktu dan peta jalan yang jelas agar localization tidak berhenti di tengah jalan (Hogan Lovells, 2024; ANTARA, 2025; ARMA Law, 2025).
Dari sisi korporasi, PT INKA harus mengonsolidasikan lini produknya dengan membangun product platform strategy yang efisien dan berorientasi modular. Pengembangan EMU komuter modular, DMU hybrid/battery, dan LRT driverless dengan komponen bersama (common parts) akan menurunkan biaya produksi dan mempermudah layanan MRO di masa depan. Di saat yang sama, investasi dalam sistem Product Lifecycle Management (PLM) dan Model-Based Systems Engineering (MBSE) perlu ditingkatkan untuk memperluas design authority domestik dan mempercepat siklus inovasi. Kemitraan teknologi dengan mitra asing hendaknya bergerak dari pola build-to-print menuju co-design, sehingga transfer pengetahuan bersifat timbal balik.
Dalam konteks pembiayaan, PT INKA perlu mengembangkan model export financing package yang terintegrasi, bekerja sama dengan lembaga pembiayaan nasional seperti PT SMI, serta perbankan sindikasi (misalnya Bank Mega) dan lembaga pembiayaan ekspor internasional (ECA). Model pembiayaan yang disertai kontrak layanan jangka panjang (availability contract dan MRO regional) akan meningkatkan nilai total proyek dan memperkuat daya saing harga. Ekspansi Banyuwangi harus dimanfaatkan sebagai export hub dengan end-of-line testing berstandar internasional dan sistem fast-track certification yang mampu memenuhi permintaan lintas negara secara cepat. Terakhir, penguatan supplier development domestik menjadi agenda strategis. Dengan membina pemasok lokal dalam komponen bernilai tinggi seperti bogie, traction converter, dan door system, INKA dapat meningkatkan TKDN tanpa mengorbankan kualitas dan reliabilitas produk.
Dengan langkah-langkah tersebut, PT INKA memiliki peluang nyata untuk menempati posisi sebagai regional system integrator di Asia Tenggara, sebuah transformasi yang akan menjadikan industri perkeretaapian Indonesia tidak hanya mandiri secara teknologi, tetapi juga kompetitif di pasar global yang semakin dinamis.
Kesimpulan
PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA saat ini berada pada titik kritis dalam lintasan industrialisasi nasional, di mana kebutuhan domestik yang semakin kompleks bertemu dengan peluang integrasi ke dalam rantai nilai industri global. Sebagai satu-satunya produsen rolling stock terintegrasi di Indonesia dan Asia Tenggara, INKA kini memegang peran strategis dalam mewujudkan dua agenda besar: pertama, mendukung pemerataan pembangunan nasional melalui perluasan layanan perkeretaapian; dan kedua, mengakselerasi lompatan menuju posisi sebagai regional player dalam industri transportasi berbasis rel. Kedua agenda tersebut menuntut keseimbangan antara orientasi pembangunan nasional dan dinamika kompetisi internasional, antara penguatan kapasitas industri dalam negeri dan keterbukaan terhadap kolaborasi lintas negara berbasis transfer pengetahuan.
Dalam horizon 2025–2029, prospek pengembangan sektor perkeretaapian nasional menunjukkan arah yang sangat menjanjikan. Kombinasi antara ekspansi urban rail (MRT dan LRT), program fleet renewal pada sistem komuter, pengembangan jaringan di luar Pulau Jawa (Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, dan Papua), serta proyek autonomous rail transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) menciptakan demand visibility yang tinggi dan stabil bagi industri manufaktur domestik. Peluang ini menyediakan ruang ekonomi bagi PT INKA untuk mencapai economies of scale sekaligus memperdalam basis teknologinya melalui learning-by-doing di berbagai proyek nasional. Namun demikian, potensi besar tersebut juga disertai kompleksitas struktural, mulai dari ketergantungan pada belanja fiskal pemerintah, ketidakpastian kebijakan TKDN, hingga keterbatasan fasilitas sertifikasi dan pembiayaan proyek, yang menuntut perubahan paradigma tata kelola dan strategi korporasi.
Pengalaman Indonesia dalam proyek berisiko tinggi, seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC Whoosh), memberikan pelajaran penting mengenai perlunya disiplin dalam project structuring dan penilaian kelayakan ekonomi proyek infrastruktur. Cost overrun, beban utang, dan ketidaksesuaian antara proyeksi dan realisasi permintaan menegaskan bahwa pertumbuhan industri perkeretaapian harus bertumpu pada kalkulasi ekonomi yang realistis, tata kelola proyek yang transparan, serta mekanisme pembiayaan yang inovatif namun berkelanjutan. Dalam konteks ini, skema public–private partnership (PPP) dengan pembagian risiko yang proporsional menjadi instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan order book tanpa membebani fiskal negara.
Selain itu, dinamika kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mengindikasikan perlunya keseimbangan antara nasionalisme ekonomi dan efisiensi industri. TKDN yang terlalu rigid dapat memperlambat inovasi dan pengadaan, sementara relaksasi tanpa arah dapat menghambat learning curve industri. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar angka kandungan lokal, melainkan technology roadmap yang jelas, yakni strategi bertahap untuk menguasai subsistem bernilai tinggi seperti traction system, signalling, braking system, dan lightweight materials. Dengan pendekatan ini, kebijakan industri dapat berfungsi sebagai mekanisme technological upgrading, bukan sebagai hambatan administratif.
Kesiapan teknologi dan sertifikasi juga menjadi aspek krusial yang menentukan posisi INKA dalam rantai pasok global. Peningkatan kapabilitas melalui pembangunan fasilitas pengujian dinamis di Banyuwangi, sertifikasi driverless system dan CBTC, serta penguatan kompetensi dalam RAMS/LCC analysis dan digital engineering merupakan langkah kunci menuju pengakuan internasional. Pabrik Banyuwangi, yang berorientasi ekspor, tidak hanya menambah kapasitas produksi, tetapi juga menciptakan industrial ecosystem baru di kawasan timur Jawa yang mendukung desentralisasi manufaktur dan pertumbuhan ekonomi regional. Dengan sistem fast-track certification dan fasilitas uji berstandar global, Banyuwangi berpotensi menjadi export-grade hub yang mempercepat time-to-market produk nasional.
Dalam dimensi kelembagaan, transformasi INKA menuju regional systems integrator menuntut perubahan paradigma manajerial dan teknologis. Perusahaan harus beralih dari sekadar build-to-print manufacturer menjadi entitas dengan design authority penuh pada varian produk strategis. Peningkatan kapasitas dalam systems integration, digital twin, dan model-based design akan memperkuat posisi INKA sebagai pusat rekayasa sistem transportasi, bukan hanya produsen sarana fisik. Di samping itu, kemitraan teknologi dengan perusahaan asing harus dibangun di atas prinsip equal footing, di mana transfer pengetahuan bersifat timbal balik dan menghasilkan co-development teknologi, bukan sekadar technology dependency.
Ekosistem kebijakan juga memegang peran fundamental dalam memastikan keberlanjutan transformasi ini. Diperlukan konsistensi antara kebijakan industri, kebijakan fiskal, dan rencana pembangunan transportasi agar arah pertumbuhan industri tidak terfragmentasi. Kolaborasi lintas kementerian, Kemenhub, Kemenperin, Bappenas, dan Kemenkeu, harus difokuskan pada penguatan industrial policy coherence, khususnya dalam penyusunan funding framework untuk proyek perkeretaapian dan program riset nasional berbasis public–industry partnership. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, integrasi kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat posisi INKA, tetapi juga membentuk arsitektur industri nasional yang resilien terhadap siklus fiskal dan tekanan eksternal.
Dengan kapasitas industri yang semakin matang, basis teknologi yang meluas melalui ekspansi Banyuwangi, serta kebijakan pemerintah yang konsisten, PT INKA memiliki peluang realistis untuk naik kelas dari national champion menjadi regional systems integrator perkeretaapian. Posisi ini tidak sekadar mencerminkan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga kemampuan untuk mengintegrasikan desain, teknologi, sertifikasi, dan layanan purna jual dalam satu rantai nilai yang terkoordinasi. Pada akhirnya, keberhasilan transformasi ini akan menjadi simbol kematangan industrialisasi Indonesia, di mana BUMN tidak hanya berperan sebagai instrumen ekonomi domestik, tetapi juga sebagai agen diplomasi teknologi dan ekonomi di kawasan.
Referensi Akademis
Amsden, A. H. (1989). Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. Oxford University Press.
ANTARA. (2020, 12 Desember). INKA exports first locomotives to Philippines.
ANTARA. (2024, 7 September). INKA factory in Banyuwangi to start full operations in 2025.
ANTARA. (2025, 6 Mei). Indonesia eases local content rules to support domestic industry.
ARMA Law. (2025, 8 Juli). Understanding Indonesia’s Local Content (TKDN) Framework.
Bappenas. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.
Bitzinger, R. A. (2016). Defense industries in the 21st century: A comparative analysis. Routledge.
Chang, H.-J. (2002). Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. Anthem Press.
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128–152.*
Goodwin, P. (1996). Empirical evidence on induced traffic: A review and synthesis. Transportation, 23(1), 35–54.*
Hill, H. (2023). The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
Hobday, M. (1995). Innovation in East Asia: The Challenge to Japan. Edward Elgar Publishing.
Hogan Lovells. (2024, 21 Agustus). Indonesia relaxes local content rules to energise green energy investment.
Indonesia Business Post. (2024, 7 Agustus). House approves Rp965 billion capital injection for PT INKA.
Indonesia Business Post. (2025, 1 Agustus). Indonesia eyes US$53 B in private rail investments to expand national network.
Jakarta Post. (2023, 28 Februari). Ministry blocks Commuter Line plan to buy Japanese trains.
Kemenhub. (2024). Laporan Tahunan Transportasi Perkotaan Indonesia.
KPMG. (2025, September). Investing in Indonesia 2025 (Chapter 3).
Krugman, P. (1991). Geography and Trade. MIT Press.
Matthews, R. (2025). Indonesia’s Defense Acquisition Strategy and Industrial Adaptation. Palgrave Macmillan.
Matthews, R., & Maharani, C. (2022). Defence industrial participation and technological learning in Indonesia. Defence Studies, 22(3), 347–369.*
Philippine News Agency. (2020, 13 Desember). Indonesian firm exports 1st 3 locomotives to PH.
PT INKA. (2025a). About INKA.
PT INKA. (2025b). PT INKA (Persero) – Company site.
PT INKA. (2025c). Light Rail Transit (LRT) Jabodebek – Product Page.
PwC Indonesia. (2024, 15 Agustus). IKN autonomous rail transit to operate commercially in 2025.
Rail Journal. (2019, 2 April). Work begins on new Indonesian rolling stock plant.
Railway Gazette. (2019, 3 Februari). PT INKA exports coaches to Bangladesh.
RollingstockWorld. (2025, 30 Mei). Indonesia tests new EMUs from PT Inka and CRRC.
Sukma, R. (2021). Indonesia and South–South Cooperation: Expanding Regional Leadership through Industrial Diplomacy. CSIS Indonesia.
The Australian. (2025, 13 Oktober). Jakarta feels belt tighten around Chinese rail debt.
The Jakarta Post. (2019, 1 April). INKA kicks off factory construction in Banyuwangi.